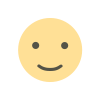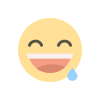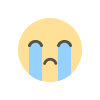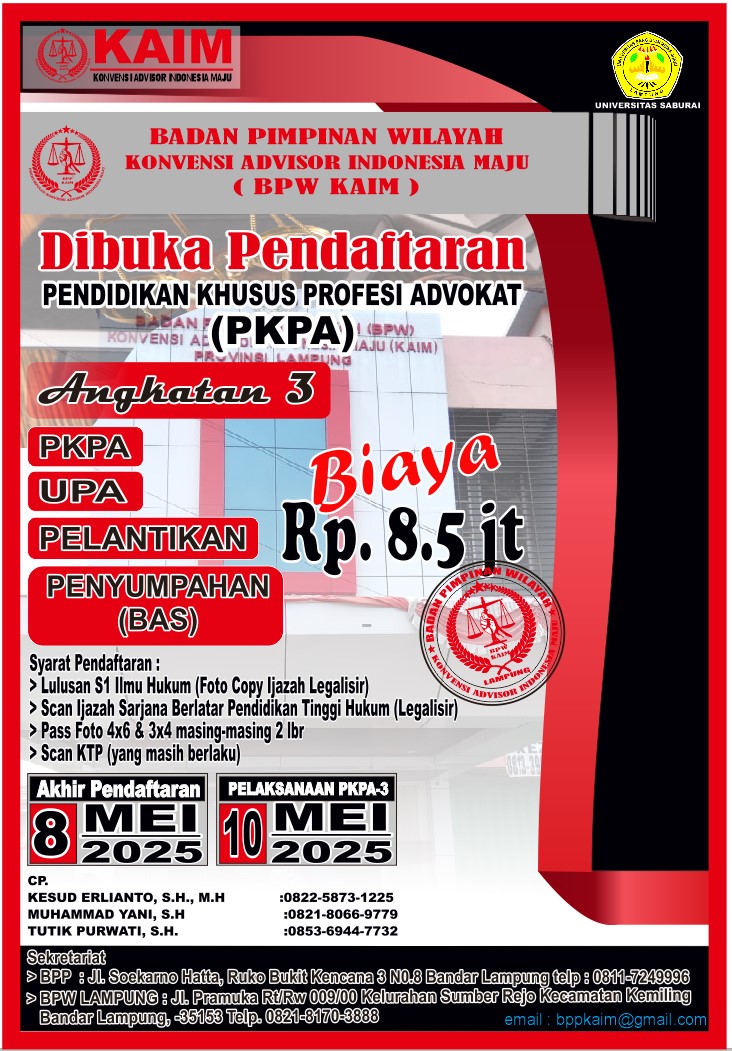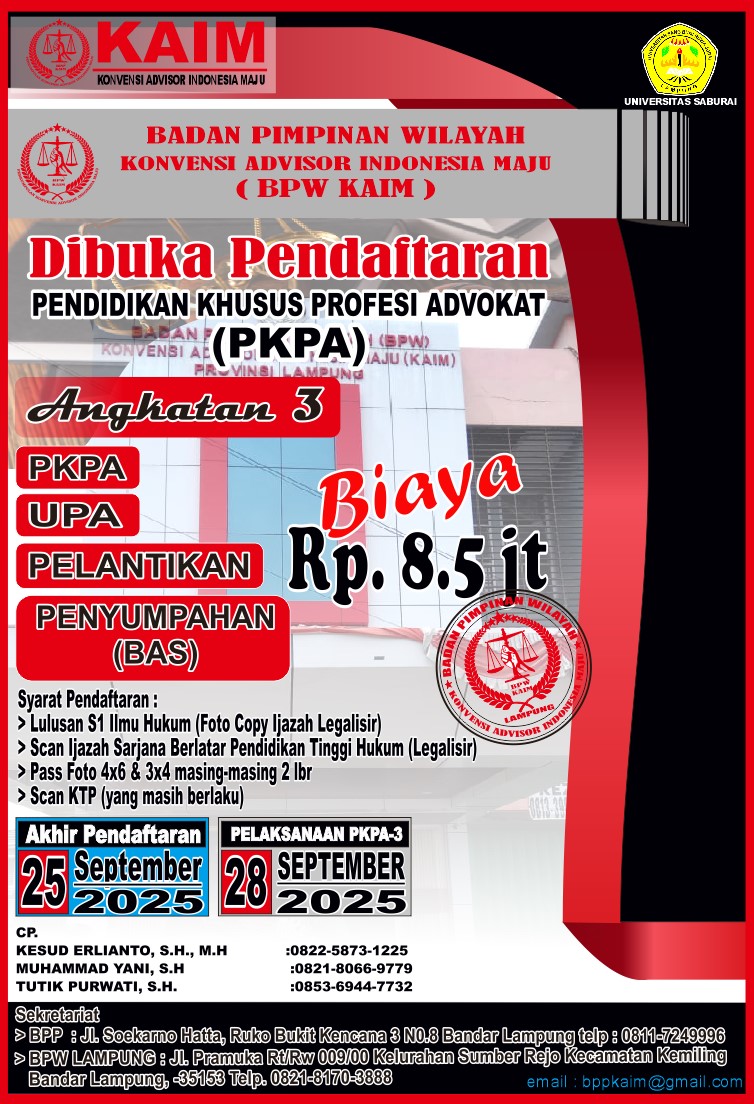Mural Sebagai Channel Kritik Kekuasaan
Oleh: Bagong Suyoto*
DINDING, makin banyak dinding berbicara di negeri. Dinding sebagai media ekspresi lebih kritis. Satu, dua mural itu dihapus aparat, lainnya bermunculan. Fenomena mural tumbuh bak di musim hunjan. Percuma mural dihapus karena sudah menjadi bagian sejarah dunia.
Belakangan ini diantara terpaan sengit pandemic Covid-19 muncul fenomena kritik kritis terhadap kebijakan dan implementasi kekuasaan via Mural. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang serba sulit akibat dampak multi-diemensi pandemic Covid-19. Ratusan triliun rupiah dari APBN dikuras untuk tangani Covid-19.
Kritik terhadap kekuasaan itu diekspresikan pada dinding-dindingan di pinggir jalan. Seperti Mural mirip Jokowi bertulis 040: Not Found menjadi sangat viral dan Tuhan Aku Lapar. Pembuatnya kini sedang diburu polisi. Sementara Presiden Jokowi meminta agar tidak terlalu mengejarnya. Mural sudah ada di dunia sejak 30 tahun lalu.
Kemudian muncul mural, “Wabah sesungguhnya adalah Kelaparan”. Mural ini pun sudah dihapus. Mural ini berada di sebuah pintu gerbang di hamparan tanah kosong jalan Wahidin Sudiro Husodo, Ciledug Kota Tangerang.
Ada juga mural; Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit. Sebetulnya banyak bermunculan fenomena mural kritik kritis terhadap kekuasaan. Tampaknya, mural kritik kritis itu mengganggu kenyaman dan kemapanan. Bagi kaum fungsionalisme, situasi ekspresi itu jika dibiarkan berlama-lama akan mengganggu stabilitas fungsi.
Mural biasanya merupakan ekspresi seni. Seni untuk seni. Ada juga untuk kepentingan yang lebih khusus, mungkin gambaran tentang kehebatan seorang raja, sejarah atau budaya suatu bangsa. Belakangan di Indonesia, mural menjadi saluran (channel) kritik kritis terhadap kebijakan dan kekuasaan. Boleh jadi ada saluran yang tersembut?
Mengapa ada mural yang mengungkapkan kritik kritis terhadap pemerintah atau penguasa di masa pandemic Covid-19? Hal ini boleh jadi akibat adanya situasi pandemic yang serba sulit, terutama faktor mencari nafkah dibatasi, sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terjepit keadaan, terjepit hutang, psikis yang mengalami stress atau depresi, dll.
Ada PSBB, selanjutnya beberapa kali PPKM darurat dan level 3-4. Sebagian masyarakat mengeluhkan dan resisten terhadap kebijakan PPKM tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memotong rantai penularan Covid-19. Kehidupan sehari-hari sangat dibatasi dan harus taat Prokes. Sebaliknya, sebagian masyarakat menilai kebijakan ini mengganggu aktivitas memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit.
Sebetulnya, ada mural tentang virus corona. Mural korupsi dan bahayanya. Mural korupsi Bansos! Pokoknya, mural menggambarkan kondisi yang dianggap curang, diskirminasi, tidak adil, dan seterusnya.
Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, upah terlalu kecil, di-PHK, tidak punya tabungan dan semacamnya hidup seperti tak punya harapan. Seperti orang-orang terbuang, tersingkir. Akibatnya, muncul benih kebencian, kenekadan, dan akhirnya memilih jalan cepat. Lalu, mengekspresikan isi pikiran dan hatinya dengan mural. Agar mendapat perhatian banyak orang atau masyarakat dan pemerintah.
Ekspresi, gambarnya semacam kartun dan tulisannya ringkas tetapi maknanya sangat jelas dan dalam. Kata-katanya langsung menusuk ulu hati! Duus, chiiiiih … Dasar mural kritik!?
Kita mesti belajar dari sejarah dan peradaban masa lalu tentang peranan kaum tersingkir, kaum miskin, kaum yang kecewa dalam kehidupan. Eric Hoffer, The True Believer diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia “Gerakan Massa” mengungkapkan; “Orang cenderung menilai suatu suku bangsa, negeri, atau kelompok dari segi anggotannya yang paling tidak masuk hitungan. Meski ini jelas berat sebelah, kecenderungan ini beralasan, karena sifat dan nasib suatu kelompok sering ditentukan oleh anggotanya yang berada di lapisan bawah.” (Eric Hoffer, 1993; 25).
“Lapisan suatu bangsa yang tidak giat, misalnya, berada di tengah-tengah. Kelompok orang taat dan rata-rata yang mengerjakan tugas bangsa di kota dan di ladang, dipengaruhi dan dibentuk oleh kelompok minoritas di lapisan atas dan bawah kelompok terbaik dan kelompok terburuk.”
Selanjutnya Hoffer menyatakan; “Orang ulung, apakah dalam politik, seni sastra, ilmu pengetahuan, perdagangan atau industri, memainkan peranan penting dalam perkembangan suatu bangsa, tetapi demikian pula halnya dengan orang di lapisan bawah – orang gagal, orang canggung, orang tercampak, penjahat, dan semua orang yang kehilangan tempat berpijak, atau belum pernah memiliki tempat berpijak, dari kalangan terhormat. Lakon sejarah biasanya dimainkan oleh lapisan terbaik dan lapisan terburuk, melangkahi golongan mayoritas di tengah-tengah.”
Alasan mengapa lapisan bawah suatu bangsa berpengaruh besar dalam menentukan jalan hidup suatu bangsa ialah karena orang dari lapisan ini sama sekali tidak mau tahu mengenai masa kini. Dalam pandangan mereka, hidup mereka dan masa kini sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka siap merobohkan dan melumatkan keduanya. … (Eric Hoffer, ibid).
Mural berasal asal dari kata “Murus” (Bahasa Latin) artinya dinding. Definisi secara luas muarl adalah menggambar di atas media dinding, tembok atau media luas lainnya bersifat permanen. Hal ini termasuk melukis yang dilakukan di lantai, meja, langit-langit.
Beberpa orang memberikan kritik yang dituangkan pada media tembok, dikenal dengan mural. Secara historis ditelusuri mural muncul dari tahun 30.000 SM. Waktu itu ada sebuah lukisan dibuat di dinding Gua Chauvet, Perancis. Lukisan itu merupakan lukisan prasejarah yang dibuat di dinding gua. Juga dibuat di pemakaman kuno di mesir, yang dipenuhi mural sejak tahun 3.150 SM. (Tempo.Co,18/8/2021).
Mural dibuat dengan berbagai cara sesuai dengan zamannya. Pada abad ke-14, mural biasanya dibuat menggunakan plester kering dengan teknik fresco secco. Teknik tersebut menjadi popular, yang berkembang sampai sekarang. Pada era saat ini dipakai kaum milenial adalah teknik marouflage, adalah teknik melukis dinding dengan cara menempelkan kanvas yang telah dilukis ke dinding. Setelah ditempelkan, kanvas akan ditekan sehingga tidak ada gelembung-gelembung udara yang menonjol dan merusak keindahan mural. (Tempo.Co,18/8/2021).
Pada saat revolusi Indonesia menuju kemerdekaan banyak ditemui mural di tembok-tembok sebagai bentuk pesan perjuangan. Mural kemerdekaan. Mural perjuangan disertai gambar Soekarno dan para pejuang. Mural: “Teroes Berjoeang Ountuk Keselamatan Bersama. Indonesia After Again the “Life-Blood” of Any Nation! Indonesia’s Inalienable Right: Her Constitution. Karena saat itu media dinding menjadi salah satu andalan.
Pada zaman milenial, banyak anak-anak muda yang mengekspresikan kelompoknya di dinding-dinding, misal nama club, group atau klan-nya. Juga kelompok-kelompok pemuda yang memuja klub sepak bola, seperti Jackmania, Bonek, Singo Edan/Arema, Maung Bandung, dll.
Kita bisa melihat mural yang berkaitan dengan pemandangan alam yang indah, dan sebaliknya kerusakan hutan karena sebagian mulai digunduli oleh korporasi. Atau suku-suku asli dari masyarakat adat yang tersingkir akibat hutannya dirambah korporasi.
Mungkin yang belum, mural berkaitan dengan pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3) dan limbah medis yang dibuang sembrangan, pun mural yang berhubungan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan sistem open-dumping. Mural leachate. Mural sampah impor!!. Bahwa negeri ini bukan tempat penampungan limbah dari negara lain.
Bagus pula, ada mural tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan global warming dan climate change. Dampaknya terhadap bumi ini? Karena global warming dan climate change berdampak serius terhadap negara kepulauan, seperti Indonesia dan negara-negara pasifik. Lalu, timbul berbagai penyakit tropis, tenggelamnya sejumlah pulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah, dll.
Apa pun ekspresi dari mural itu, baik yang lembut, sedang/biasa-biasa saja atau dalam bentuk kritik yang pedas mesti harus dicermati secara seksama, hati-hati dan penuh pandangan ke depan. Sebab, semua itu muncul pasti ada sebab-sebabnya. Dan, lebih baik mereka diajak diskusi secara ilmiah dan mendalam untuk kemajuan bangsa negara Indonesia ini. Saluran demokrasi harus dibuka seluas-luasnya.
* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)

 REDAKSI
REDAKSI