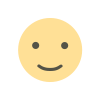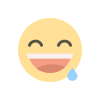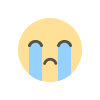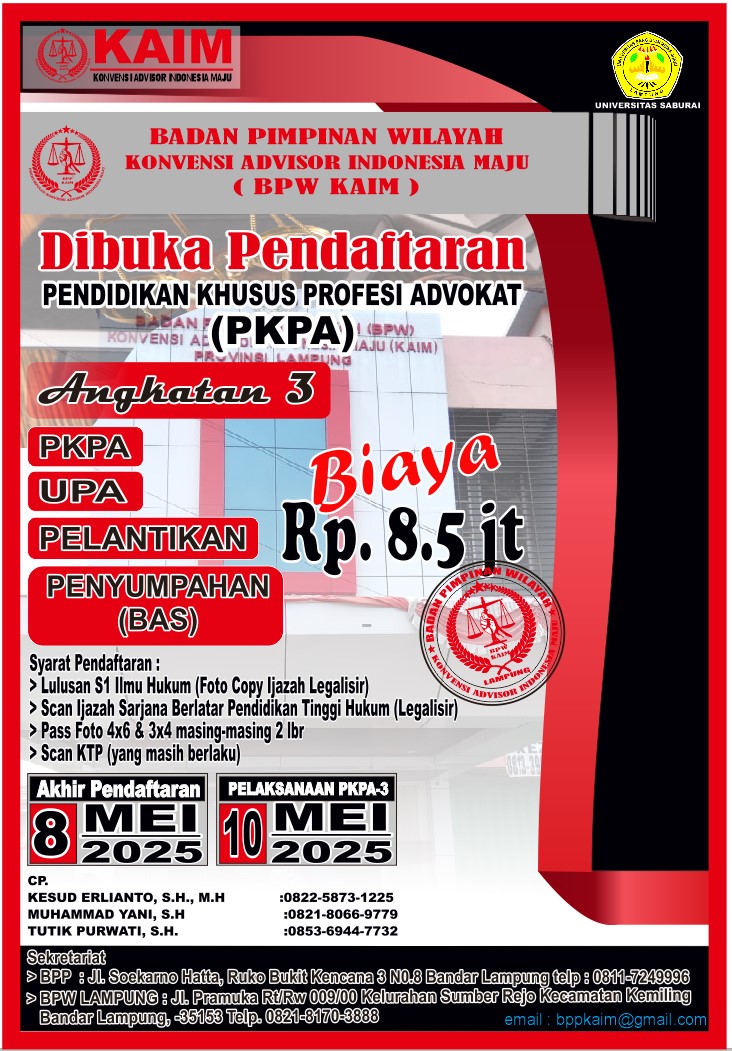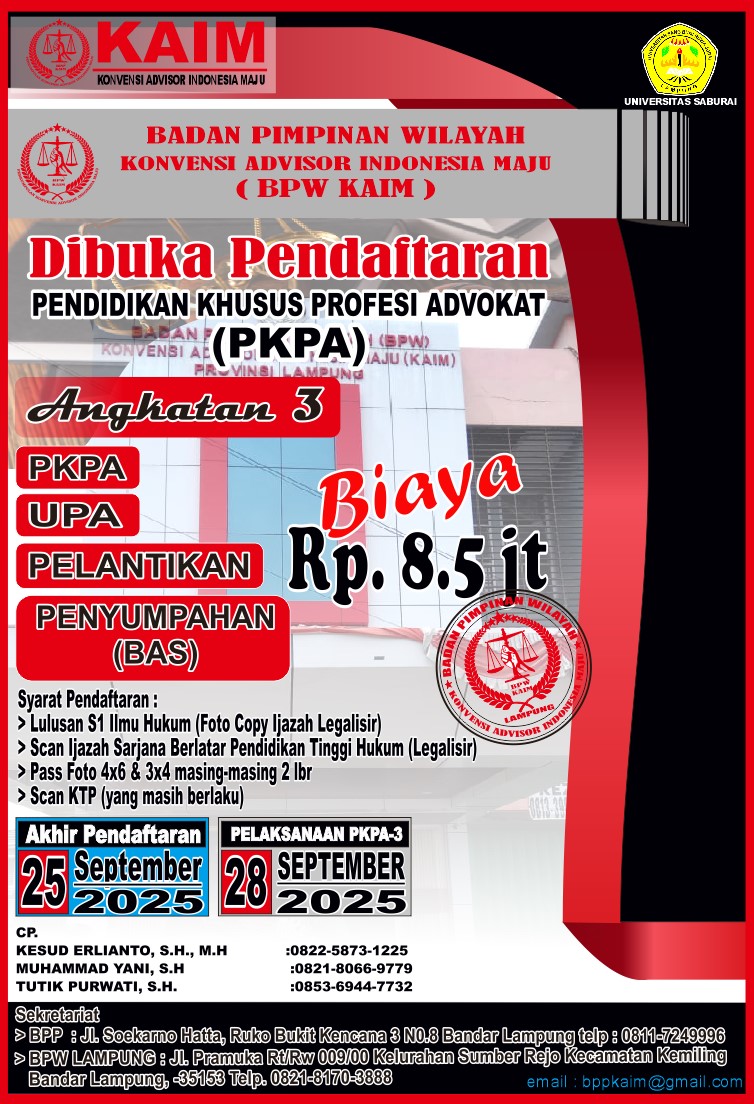Jejak Awal Nasionalisme Progresif Di Tanah Hindia Belanda (2-Bersambung)
Hampir bersamaan dengan kelahiran Tirto Adhi Soeryo di Blora, situasi di tanah Jawa sedang memasuki sebuah tatanan jaman kolonial baru, dibandingkan dengan masa sebelumnya, Jaman ini disebut dengan zaman modal. Jaman modal ini ditandai dengan kebijakan politik kolonial yang lebih liberal, dengan turut beroprasinya Kapitalisme swasta Belanda di tanah Jawa.

Awal abad XX adalah sebuah zaman baru bagi Politik Kolonial Belanda di Hindia, semboyan dari zaman baru ini adalah “Kemajuan menuju modernitas”. “Kemajuan” dalam arti dibawah pengawasan Belanda, dan “Modernitas” seperti yang ditunjukkan Belanda di Hindia dipahami sebagai peradaban bangsa Barat.
Penulis : Lucas Dwi Hartanto *)
Kaum bangsawan kala itu berkesempatan mengenyam pendidikan sekolah Belanda, dan memiliki sedikit hak istimewa berupa forum previligiatium, yang memungkinkan dirinya bebas dari hukum siksa pemerintah kolonial Belanda. Posisi sedikit hak istimewa yang dimiliki Tirto Adhi Soeryo ini, nantinya akan lebih mempermudah dirinya dalam membidani kelahiran Identitas nasionalisme progresf bagi Bangsanya yang baru.
Pada masa sebelumnya, hampir semua eksploitasi ekonomi hanya dimonopoli oleh pemerintah Belanda. Secara formal praktek liberalisasi tatanan ekonomi-politik kolonial ini ditandai dan diatur dalam Undang-undang Agraria tahun 1870 (Zaman Bergerak, hlm. 10).
Bentuk liberalisasi pada zaman modal ini tercermin dari banyaknya perusahaan-perusahaan swasta belanda (modal swasta) yang mulai beroperasi secara intensif, dengan membuka lahan-lahan subur perkebunan secara masif dan luas di tanah Jawa, juga di tanah Sumatera.
Bersamaan dengan itu, pada tahun 1870 jalur kereta api pertama di Hindia belanda dibangun, yaitu jalur yang menghubungkan antara Vorstenlanden (daerah kerajaan) dengan Pelabuhan utama, yaitu pembangunan jalur kereta api dari Surakarta ke Semarang.
Jalur pertama ini dioperasikan oleh perusahaan swasta Belanda bernamaNederlandch Indische Spoorweg (NIS). Beberapa tahun kemudian menyusul dibangunnya jalur-jalur kereta api baru, yang menghubungkan kota-kota dipulau Jawa sebagai pusat perdagangan, dengan daerah Perkebunan subur, Pabrik dan Industri pengolahan, dan tentu saja semuanya bermuara ke Pelabuhan untuk kemudian dipasarkan ke Eropa dan negara Induknya Belanda.
Selain Perkebunan dan jalur kereta api, di tanah Jawa pada saat itu juga mulai dibangun Pabrik-pabrik yang mengelola hasil perkebunan, salah satunya yang tertua adalah berdirinya Pabrik Gula di Tasik Madu dan Colomadu pada awal tahun 1870 di Surakarta, yang nantinya akan diikuti oleh munculnya berbagai macam pabrik-pabrik dan Industri besar dan kecil, serta berbagai usaha kerajinan tangan lainya di tanah Jawa. (Sang Pemula. Hlm : 16).
Usaha-usaha perkebunan Swasta, pendirian pabrik-pabrik swasta pengolahan hasil perkebunan dan berdirinya Industri-industri pengolahan ber-sekala besar dan kecil ini, memicu semakin maraknya indsutri dan jasa perdagangan di Hindia Belanda pada akhir abad XIX dan awal abad XX ini.
Selain pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan Swasta Belanda, kaum Bangsawan pribumi seperti para raja, pangeran dan para bangsawan Bumiputera lainya juga mulai terlibat secara aktif terlibat. Mulai dari menyewakan tanah kerajaan, menanamkan modalnya, mendirikan pabrik Gula dan lain-lain. Para pedagang dan pengusaha Thionghoa, Arab dan Timur asing di Jawa juga sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi pada masa Zaman Modal ini.
Zaman baru ini digambarkan sebagai “ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan”, dimana kepulauan Hindia dari Sabang sampai Merauke kini berada dibawah kontrol Belanda secara politik, kebijakan rust and order atau stabilitas keamanan untuk mengamankan eksplotasi kapital ditegakan diatas wilayah tersebut. (Zaman Bergerak, hlm : 36).
Zaman moderen ini dalam sejarah sering di katakan sebagai Era Politik Etis. Tatanan zaman modal dan dan zaman moderen ini merupakan proses awal masuknya Industrialisasi moderen kolonial dan Imperialisme di pulau Jawa, yang memberikan dampak serta implikasi luas bagi kaum Bumiputera di tanah Hindia, baik dikalangan rakyat biasa atau kebanyakan, maupun di kalangan keturunan bangsawan yang berasal dari kelas menengah Bumiputera, yaitu kaum Bangsawan-Priyayi yang rata-rata bekerja sebagai Ambtenaar (Pegawai Negeri) bekerja pada Jawatan dan Dinas Pemerintah Belanda.
Di daerah perkotaan muncul orang particculier yaitu pekerja kantoran pada perusahaan swasta yang berbeda dengan pekerja kasar kebanyakan dan berbeda dengan Bangsawan-Priyayi lama yang bekerja pada dinas pemerintahan belanda, orang particculier ini adalah kelas menengah penerima gaji, yang memiliki karakter dinamis, bersifat Kota, Moderen dan terpelajar, hasil pendidikan Eropa gaya Belanda. (Zaman Bergerak, hlm : 36).
Selain munculnya kelas pekerja upahan, banyak pula dari kalangan Bangsawan-Priyayi yang juga mulai beralih menjadi pengusaha swasta, juga makin tumbuhnya para pedagang dan pengusaha Tionghoa, Arab dan timur jauh lainya.
Selain itu semakin banyak kaum bangsawan terpelajar, kaum Indo-Blasteran, juga para pemodal dan pekerja Belanda dan eropa yang membuka usahanya di Hindia Belanda.
Begitulah gambaran umum situasi Zaman Modal di tanah jajahan Hindia-Belanda yang bergerak secara cepat dan dinamis.
· Narasi Pemikiran Tirto Adisuryo dan Identitas Feodalisme Priyayi Jawa dalam Cengkeraman Sistem Kolonialisme Hindia-Belanda.
Dalam konteks situasi zaman modal dan zaman moderen di Hindia-Belanda inilah, sosok Tirto Adhi Soeryo lahir, tumbuh dan berkembang. Memasuk Zaman modal kedua atau Zaman moderen ini (pada periode sebelumnya disebut zaman modal pertama), kemudian menghantarkan tatanan kolonial Hindia belanda memasuki sebuah masa yang disebut Reorganisasi dan reformasi pemerintah Kolonial, yang lebih dikenal dengan istilah Era politik Etis (zaman modal kedua). Era Politik Etis ini juga sering dikaitkan dengan lahirnya zaman moderen dalam berbagai bidang di Negeri jajahan Hindia-Belanda.
Pengalama pribadi yang pahit dan menyakitkan yang dialami RA. Tirtonoto dan keluarganya, membuat dia sangat membenci kelakuan pemerintahan Kolonial Belanda yang banyak merugikan kaumya (Bangsawan). Tentang hal ini Tirto mengungkapkan-nya dalam karya semi autobiografinya Busono (Sang Pemula. hlm : 28). Dikemudian hari Tirto juga banyak mengkritik sikap-sikap dan sepak terjang kastanya sendiri yaitu para bangsawan-priyayi Jawa, dia menggambarkan bagaimana watak Feodalisme pada kastanya seperti ini :
Dalam penggambaran Pramudya Ananta Toer dalam Sang Pemula, sikap Tirto ini tercermin pada apa yang dia ungkapkan yaitu :
Kaum Bumiputera di Hindia Belanda pada masa itu umumnya mengalami beban ganda tekanan penindasan, pertama tekanan penindasan dari Kolonialisme Belanda sebagai bangsa penjajah, dan kedua dari para bangsawan-priyayi sebagai Ambtenaar (pegawai kolonial) yang banyak mengambil banyak keuntungan tidak wajar dari jabatan-jabatan yang diembanya, praktek upeti, korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan kecurangan terhadap rakyat dilapisan bawah lainya banyak di praktekan.
Krisis yang dialami oleh kaum bangsawan-priyayi Jawa dalam menghadapi arus besar zaman moderen yang lebih dinamis ini, kemudian mewarnai situasi ekonomi, politik, sosial dan budaya di Hindia Belanda pada Awal abad XX.
Situasi ini pada akhirnya menghantarkan sayarat-sayarat baru, kesadaran baru dan kondisi sosial baru menuju kearah identitas nasional sebuah bangsa terjajah, yaitu kaum Bumiputera dengan cara pandandang baru terhadap identitas dirinya.
*) Penliti Sastra Sejarah dan Blogger
Baca Bagian Ke satu disini https://monologis.id/jejak-awal-nasionalisme-progresif-di-tanah-hindia-belanda-1-bersambung

 DEDI ROHMAN
DEDI ROHMAN