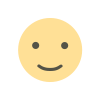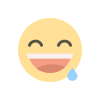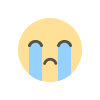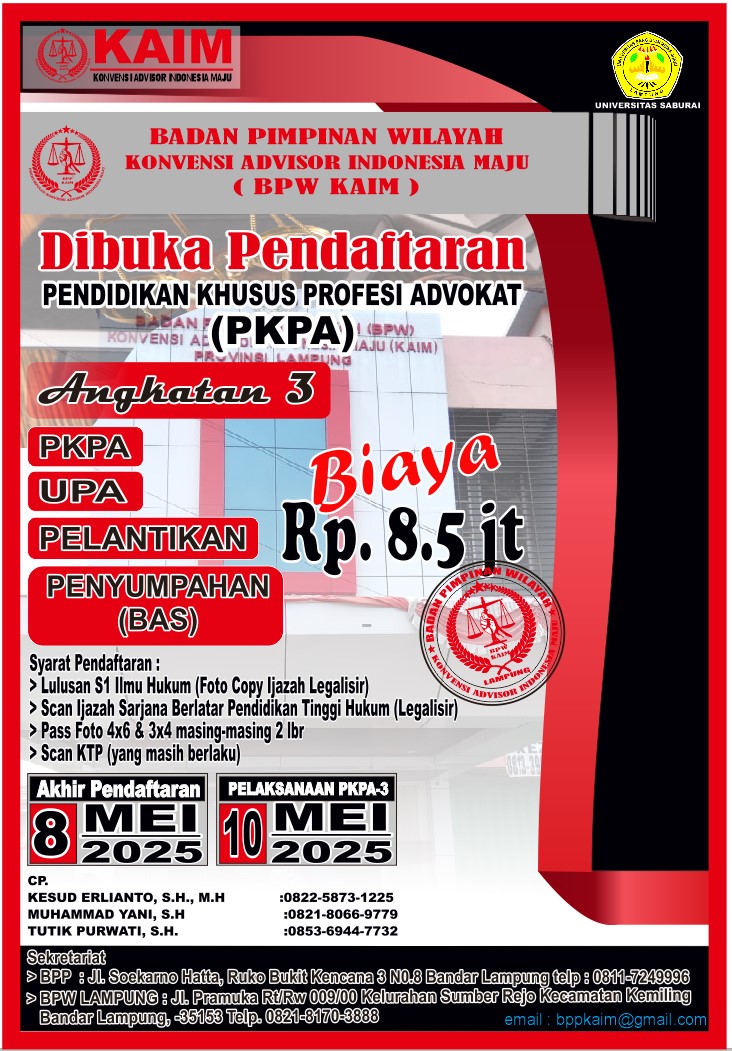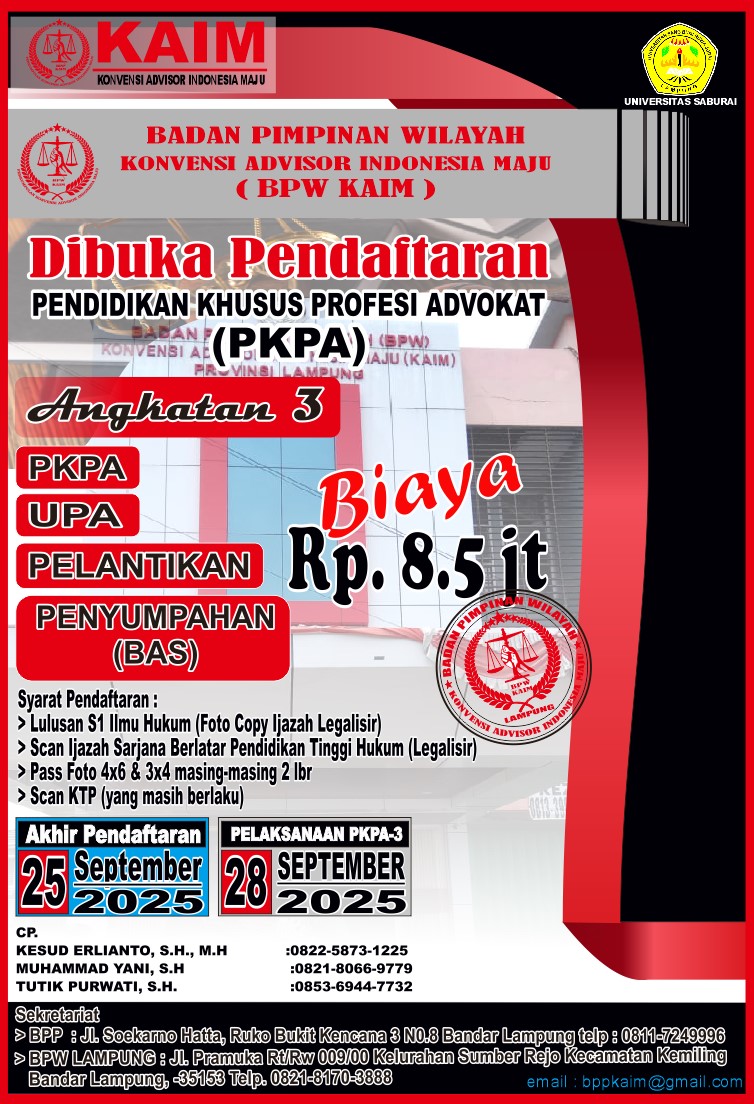Tafsir Bebas Presiden Jokowi Dengan Pakaian Suku Baduy Ketika Sidang MPR RI
Oleh: Bagong Suyoto*
PRESIDEN RI Jokowi memaikai pakaian adat Baudy dengan tas tireb ketika menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang MPR RI, 16 Agustus 2021. Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggunakan pakaian Adat Mandar, dan Ketua DPR RI memakai pakaian adat Bali.
Presiden Jokowi sudah beberapa kali memakai pakaian adat ketika menyampaikan pidato kenegaraan Sidang MPR RI dan pada saat menjadi inspektor upacara HUT Kemerdekaan RI. Kini 2021 HUT RI ke-76. Jelas sekali Presiden senang pakaian adat. Perlu tafsir bebas dan makna dari kemauan Presiden Jokowi berpakain Suku Baduy?!
Pustita Susanti (djn, 6/11/2019) mengungkapkan seputar pakaian Suku Baduy. Banten memiliki suku asli, dikenal dengan Suku Baduy. Suku ini masih memegang erat hukum adat dan kebudayaan mereka. Suku Baduy terdiri dari Suku Dalam dan Luar. Hal ini dibedakan dari pengaruh luar dalam kebudayaannya. Masing-masing punya pakaian adat.
Pakaian Suku Baduy Dalam berasal dari zaman Sangsang. Pakaian mereka berwarna putih polos yang digunakan secara disangsangkan atau digantung di badan, bahan dari serat kapas asli. Memiliki lubang di leher tanpa kerah dan lubang bagian lengan. Zaman Sangsang pun pakaian itu tidak punya kancing, saku dan hanya dijahit dengan tangan.
Bawahan pakaian Baduy Dalam, mengenakan sarung warna hitam atau biru tua yang dililit di pinggang. Mereka menggunakan ikat kepala dari kaian warna putih.
Berbeda dengan Suku Baduy Luar, justru memakai pakain hitam. Bajunya disebut baju kampret (baju kelelawar) sebab warnanya hitam. Bentuk baju Baduy Luar sedikit modern karena dijahit dengan mesin, ada kancing, kantong, dan tak harus dari kapas murni. Baduy Luar juga sering memakai ikat kepala berwarna biru tua dengan corak batik.
Berdasar kajian, bahwa pakaian adat yang dipakai Presiden Jokowi adalah pakaian suku Baduy Luar. Merupakan suatu bentuk penghargaan khusus terhadap suku dan segala bentuk kebudayaan dan adat istiadatnya serta. Merupakan suatu tafsir bebas ala penulis.
Suku Baduy perlu dihargai dan diberikan kuasa terhadap ruang dan lahan mencari nafkah guna melangsungkan hidup. Hak kepemilikan dan penguasaan ruang dan sumber daya alam adalah sangat penting.
Suku Baduy sangat patuh terhadap kebudayaan dan warisan nenek moyang. Juga mencintai dan sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Mereka selalu menjaga hutan agar tetap lestari. Ketika hutan-hutan keramat dan pepohonannya dibabat demi alasan pembangunan maka Baduy akan menjerit dan menangis.
Suku Baduy bertani dengan sistem pertanian selaras alam, biodinamika, semacam organic farming. Sistem itu dipertahankan selama ratusan tahun. Mereka senang memuliakan tanaman endemic, seperti padi varietas local, tanaman herbal, pepohonan, dll. Mengambil dari alam seperlunya untuk memenuhi kebutuhan makan. Hidupnya sederhana dan hemat.
Dan, mereka sampai kini mempertahankan lumbung pangan. Suku Baduy punya sistem dan model kemandiran pangan. Tetapi masyarakat sekarang, lumbung pangannya ada di toko/ warung, ada di luar negeri, seperti di Vietnam, Thailand, RRT, Amerika Serikat, dll. Berarti lumbungan pangannya kita di negara orang lain, berarti harus impor pangan.
Swasembeda pangan. Setiap memetik padi diadakan pesta Seren Taun. Upacara adat panen padi dilakukan setiap tahun. Suatu wujud rasa syukur terdahap panen melimpah dan terhindar dari berbagai penyakit. Pesta adat Sunda ini dilakukan penduduk Desa Kanekes, Kabupaten Lebak Banten. Tempat lain diantarananya Kasepuhan Banten Kidul Desa Ciptagelar Sisolok, Kabupaten Sukabumi; Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya; Desa Cigugur Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Desa Sidang Bareng, Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor; dll.
Dimana, sebagian besar desa di nusantara ini sudah kehilangan lumbung pangan akibat ekspansi sistem pertanian “Green Revolution” dan lompatan besar “Gene Revolution”. Green revolution merupakan sistem pertanian modern yang menggunakan benih unggul (hybrid eeds), pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan intensif modal dan teknologi. Sietm pertanian modern itu dalam banyak kasus menimbulkan malapetaka tersendiri dan mencabut kedaulatan pangan rumah tangga petani. Muncul petani marginal tersingkir dari asset produksinya.
Perlahan-lahan sistem pertanian modern tak mampu mencapai tujuannya, malahan kelaparan menghantui penduduk dunia. Tanah semakin gersang dan sejumlah zat hara dalam tanah lenyap, maka ketak-berhasilan revolusi hijau sangat tampak. Sistem pertanian modern ini mempercepat laju pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengancam kesehatan manusia. (Bagong Suyoto, 2008).
Selama pandemic COVID-19, dampaknya terhadap suku Baduy. Berbagai media memberitakan, kasus positip COVID-19 hingga kini tidak ditemui di lingkungan masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Tak ada warga Baduy terinfeksi COVID-19. Padahal kabupaten tersebut saat ini berstatus zona merah lantaran tinggainya kasus penyebaran COVID-19. Hal ini setelah Puskesmas Cisimeut Lebak melakukan tes antigen beberapa waktu lalu. (Merdeka.com, 1/7/2021) yang dilansir dari Antara.
Suku Baduy sangat taat mematuhi titah dari tetua. Salah satunya, tidak banyak bepergian ke luar daerah. Juga wisatawan yang datang harus mentaati Prokes, seperti pemeriksaan suhu, memakai masker, cuci tangan, tak berkerumun, tak boleh buang sampah semberangan. Juga lebih banyak beraktivitas di ladang masing-masing.
Kata tetua adat Kanekes Jaro Saija, bahwa prokes diterapkan secara ketat dan tegas, warga tak boleh ke luar daerah, warga Baduy yang merantai diminta segara pulang. Sebelum sampai di kampong harus memerksakan kesehatan ke Puskesmas serta meminum ramuan tradisonal yang terbuat dari rempah-remah, yakni cikur dan jahe merah. (Merdeka.com, 1/7/2021).
Belakangan ada satu satu warga terpapar virus tersebut. Kepala Puskesmas Cisimeut Maytri Nurmaningsih mengatakan, ada warga yang telah melahirkan kemudian mengalami gejala mirif COVID-19. Kemudiankan dilakukan tindakan rapid antigen dan ternyata postip. Perempuan itu setelah melahirkan dirapid antigen pada 25 Juli, terus PCR-nya pada 3 Agustus 2021. (detiknews, 16/8/2021).
Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI dan para pembesar menunjukkan suka, senang, cinta terhadap pakaian suku di Indonesia. Maknanya, jelas di mata publik. Hal ini perlu ditunjukkan pada kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kedaulatan suku-suku asli di nusantara. Hak ruang hidup, hak terhadap sumberdaya alam/mencari nafkah, hak rasa aman, hak bersuara, hak peroleh pendidikan, hak kesehatan, dll sebagai hak paling dasar harus diberikan oleh negara. Indonesia ini ada karena adanya suku-suku bangsa tersebut.
Indonesia adalah negara besar dan mempunyai keanekaramagan flora fauna dan sangat unik. Luas Indonesia sekitar 1,905 juta km2 dengan populasi 270,7 juta jiwa (World Bank, 2019). Terdiri dari 17.000 pulau dengan lebih 700 bahasa daerah, lebih dari 300 kelompok etnik/suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa. (Sensus BPS,2010).
Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sedang di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil, beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku ini tidak mutlak dan tidak jelas, akibat perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. (Indonesia.GO.ID). Sedang penduduk Indonesia lebih 60% tinggal di Pulau Jawa dan terkosentrasi di wilayah Megapolitan Jaboadetabek sekitar 41 juta jiwa.
Sementara itu kita mengenal istilah indigenous people. Suku pribumi merupakan penduduk awal dai suatu tempat dan membangun kebudayaannya, bukan pendatang dikenal dengan indigenous people. Masyarakat adat di Indonesia sekitar 20% atau 50-70 juta dari penduduk Indonesia. (AMAN, 1999).
Sehingga mengelola Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, agama dan keyakinan diperluakan suatu perekat. Jika tidak akan timbul masalah, perpecahan tak terbendung. Dan, Indonesia akan rontok! Menurut Soekarno, Presiden Pertama Indonesia, perekat itu adalah Pancasila.
Pancasila dan nilai-nilainya dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan peradaban dunia serta ideologi besar dunia, yakni Kapitalisme, Komunisme dan Islam. Ancaman secara internal seringkali dihadapkan pada persoalan SARA, ketidakadilan, diskriminasi, aliran agama, upaya pembentukan negara berbasis agama, dll.
Sedang ancaman eksternal secara geostrategi dan kekayaan sumber alam, Indonesia jadi incaran sejumlah negara maju. Mereka sudah memasuki Industrial Society dan Post-Industrial Society. Banyak negara maju melirik dan ingin menguasai Indonesia. Bisakah Pancasila bertahan?
Posisi masyarakat Indonesia sekarang berada dimana? Secara antropologis dan sosiologis, masyarakat suku-suku di Indonesia, ada berada pada level berburu dan mengembara, bertani, industri dan sebagian meunju post-industri. Hipotesa Daniel Bell (Post Industrial Society, 1973, Culture Contradiction, 1976) mengatakan, dunia barat sedang mengalami transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat post-industri. Demikian juga Jepang, RRT, Korea Selatan, Singapore, dll.
Bagaimana mengelola masyarakat yang terus berkembang menuju masyarakat industri dan post-industri, sementara di pelosok-pesolok kepulauan ini masih banyak dijumpai kehidupan masyarakat relatif primitif dan tradisonal? Satu sisi ada yang tertinggal dan di sisi lain ada yang sangat maju. Kondisi tersebut akan berkaitan dengan upaya menata struktur sosial masyarakat dan konskuensi-konskuensi politik serta kekuasaan. Juga, tentu berhubungan dengan dukungan penguasaan sumberdaya (alam), seperti pemberian hak pengelolaan lahan, hutan dan sumber daya lainnya.
Salah satu dukungan konkrit pemerintah/negara adalah pemberian Status Pengakuan Wilayah Adat. Pada perayaan HUT RI ke-76, Badan Register Wilayah Adat (BRWA) memperbaruhi status tersebut. BRWA meregistrasi 1.034 wilayah adat dengan luas sekitar 12,4 juta hektar, tersebar di 29 provinsi dan 136 kabupaten/kota. Status pengakuan wilayah adat berdasar kebijakan daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan. Ada 154 wilayah adat yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dengan luas 2,46 juta hektar atau sekitar 19,8% dari total wilayah adat di BRWA.
Pada wilayah provinsi dan kabupate/kota telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pengakuan Masyarakat Adat terdapat 617 peta wilayah adat dengan luas 7,66 juta hektar. Sementara itu, masih ada sekitar 2,31 juta hektar wilayah adat belum memiliki payung hukum pengakuannya. (Kasmito Widodo, 17/8/2021).
Dari 12,4 juta hektar peta wilayah adat teregisterasi di BRWA, potensi hutan adatnya mencapai sekitar 8,35 juta hektar. KLHK RI menerbitkan 75 surat keputusan pengakuan Hutan Adat dengan luas sekitar 56.903 hektar atau sekitar 0,68% dari potensi Hutan Adat saat ini.
Dalam konteks ini, kita masih mempunyai pekerjaan besar menyelesaikan berbagai pembangunan, pengakuan hak-hak masyarakat, reforma gararia, tantangan berat dalam menghadapi persaingan global, penetrasi informasi tenologi, dan yang mengerikan pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change). Ancaman yang terakhir itu sangat serius terhadap negara kepulauan Indonesia.
* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)

 REDAKSI
REDAKSI