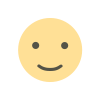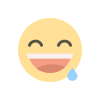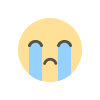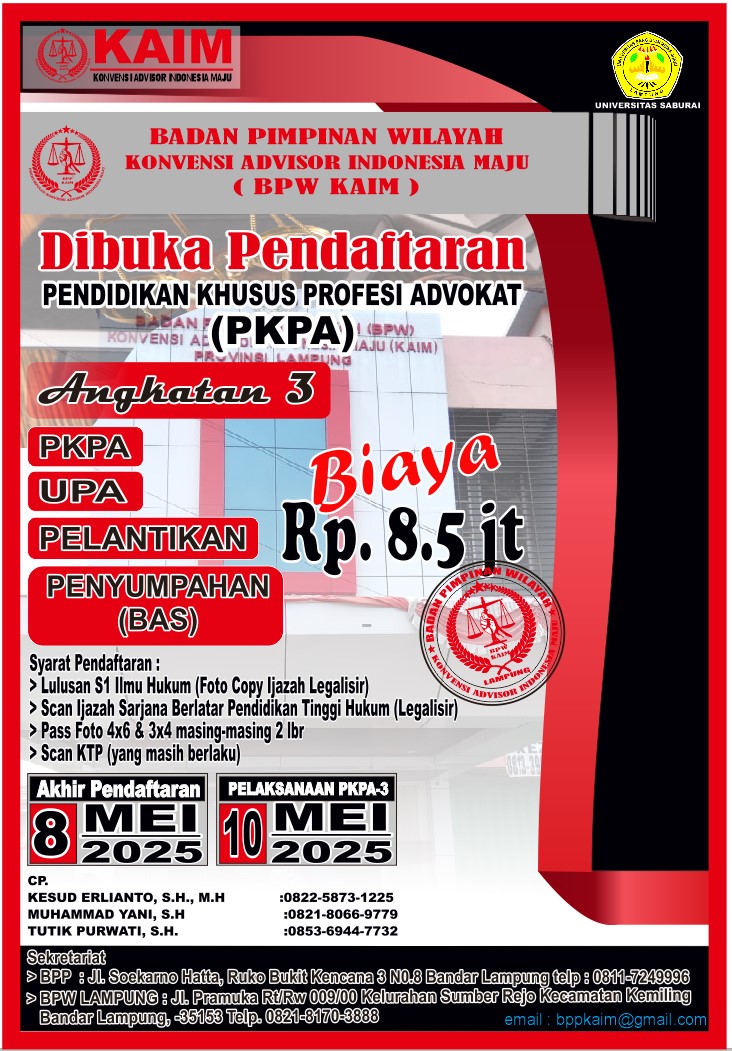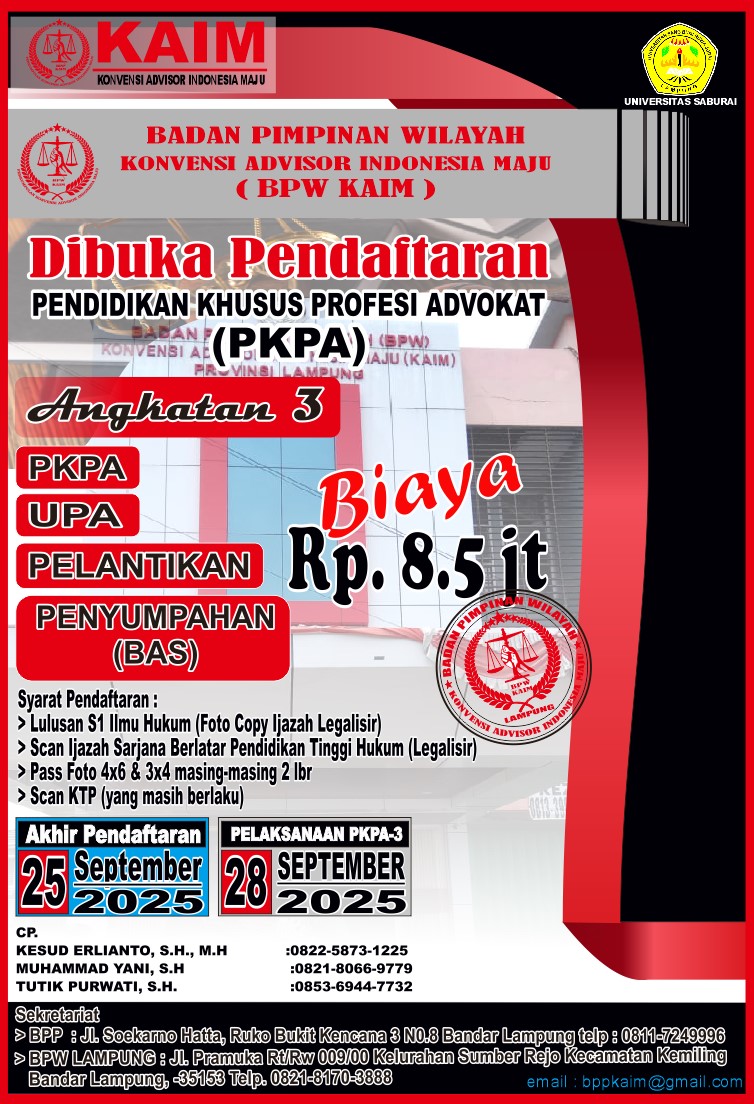Sejumlah Komunitas Ingin Olah Sampah Dari Sumber, Butuh Dukungan Pemerintah
Oleh: Bagong Suyoto*
SEJAK bulan Januari sampai 10 Agustus 2021 Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) melakukan investigasi dan advokasi pengolahan sampah dari sumber di sejumlah tempat. Kesimpulannya, banyak komunitas yang bekerja keras mengolah sampah di tingkat sumber dengan modal secara swadaya dan kolaborasi.
Usaha mereka sangat riel menjalankan mandat Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perpres No. 97/2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mereka secara nyata mengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) dari sumber.
Banyak cerita suksus komunitas dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) sukses olah sampah dari sumber. Berikut ini disajikan salah satu cerita singkat komunitas pengolah sampah dari sumber atau dekat sumber.
Selama ini kegiatan mereka telah memberikan manfaat besar bagi warga sekitar, membantu pemerintah dan sekaligus melestarikan lingkungan hidup. Setiap orang menghasilkan sampah, namun tidak setiap orang mau mengurusi sampahnya. Bau busuk, kotor, apalagi ada belatung, lalat, tikus, menyerah deh…
Menurut Suwiryo Hadistri Bara (55 thn) Ketua TPS 3R Bara & BS, bahwa apa yang selama ini dilakukan dalam olah sampah sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah, mengembalikan sampah menjadi sumber daya, mengolah sampah di sumber, menciptakan lapangan kerj dan pendapatan masyarakat sekitar.
Lanjut Bara, yang juga Ketua Umum Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO), jika tidak dikumpulkan dan dikelola di suatu tempat, maka sampah tersebut banyak ditemui dibuang di lahan kosong, pinggir jalan, saluran air, daerah air sungai, bahkan ke sungai. Berarti akan menambah kondisi kotor, jorok dan mencemari lingkungan.
“Apa yang kami lakukan agar bisa makan cukup. Dengan mengolah sampah bisa mendapat rezeki, juga tetangga bisa bekerja, terutama buruh kasar dan buruh tani yang tak punya pekerjaan”, kata Bara.
“Daerah utara (maksudnya Bekasi Utara) setelah tanam padi tak ada kerjaan, tak ada duwit kontan, padahal kebutuhan dapur, jajan anak, kondangan harus … Pada bingung! Dengan adanya TPS 3R, warga sekitar bisa kerja mendapat uang. Keberadannya sangat membantu mereka”, tambahnya.
Bara mempunyai tempat pengolahan sampah terletak di Kampung Kobak Rante Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Tempat ini dikenal dengan TPS 3R Bara & BS. Luasnya sekitar satu hektar. Usaha ini menciptakan lapangan kerja hampir 200 orang. Di sini ada pengangkutan sampah, pengorek sampah, pemilahan sampah, juga sebagai pengepul plastik, kertas, logam, dll. Pun ada teknologi pembakar sampah skala kecil, tarapnya baru uji-coba.
Bara pingin punya mesin press, teknologi composting, conveyor-belt (datar dan input), mesin pengayak kompos, mesin pencacah plastik. Supaya semua dapat diolah dan sisa-sisa sortir dan plastik kecil-kecil yang tak laku-jual diolah mesin pembakar dan abunya dijadikan pavin-block, bata, dll. Ia ingin mengimplementasikan waste to energy (WtE). Jadi, berbagai teknologi pengolah sampah tersedia dan bisa jadi percontohan.
Bara punya Barisan Rakyat Garda Ekonomi Desa, dengan slogan unik, kocak, agak heperbolis “Edan Tapi Mapan”. Sehingga banyak orang penasaran (curious). Banyak orang penasaran pingin tahu apa maknanya (showing curiosity). Stiker tersebut dipasang di rumah, tempat kegiatan, mobil, dll. Dulunya, Bara fokus pada sektor pertanian sebab wilayahnya lahan pertanian masih relaif luas, terutama sawah irigasi teknis. Kini sawah-sawah itu perlahan menyempit akibat berbagai pembangunan, terutama perumahan (real estate), pabrik, usaha ayam potong, fasilitas public, dll.
Namun, sejak lima belas tahun lalu, ia lebih tertarik pada sampah. Kemudian Bara merintis usaha sampah bertahan hingga kini. Belakangan banyak anak muda ikut dalam usaha mengolah sampah tersebut. Walhasil, terbentuklah komunitas pengolah sampah.
Komunitas ini membuka usaha, dikenal pengepul rongsokan atau lapak sampah. Istilah kerennya Pusat Daur Ulang Sampah (PDUS), Pusat Olah Sampah 3R atau TPS 3R. Sebagian posisi mereka masuk sektor informal (pelapak, pemulung, buruh sortir, dll). Kegiatan mereka ada beberapa tipologi.
Usaha tersebut semakin banyak tumbuh dan menjadi suatu kekuatan ekonomi tersendiri dalam menopang industri daur ulang dalam negeri. Jika dikaji secara ilmiah, kegiatan komunitas itu bagian dari rantai circular economy. Selain itu, ada pula bank sampah, sedang ditumbuh-kembangkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia.
Dalam pengelolaan sampah dikenal istilah ekonomi sirkular (circular economy), merupakan salah satu prioritas Pemerintah RI dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mendorong pertumbuhan industri daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi sampah yang masuk ke lingkungan (solusi ekologi) – sekaligus mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis sampah untuk dimanfaatkan oleh industri (solusi ekonomi). Lihat Kajian Daur Ulang Plastik dan Kertas Dalam Negeri diterbitkan Ditjen PLSB KLHK, 2021.
Pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri melalui Menteri Perdagangan No. 482 Tahun 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.235/MENLHK/PSLB/PLB.3/5/2020, Menteri Perindustrian No. 715 Tahun 2020 dan Kepala Kepolisian RI No. KB/1/V/2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri pada tanggal 27 Mei 2020. SKB ini memuat kesepakatan penyusunan bersama peta jalan (road map) dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri sebagai pengganti bahan baku impor limbah non B3, khususnya kelompok plastik dan kertas.
Tipologi pertama, ada komunitas yang hanya mengumpulkan sampah dari sejumlah tempat, misal perumahan, pasar, kantor, mall, apartemen, kemudian sampahnya dipilah dalam bentuk sampah campur/gabrugan, seperti berbagai jenis plastik disatukan, berbagai jenis logam, berbagai jenis beling, berbagai jenis kertas, dll. Harga plastik gabrugan Rp 1.500-2.500/kg. Selanjutnya disortir dalam bentuk partai besar. Aktivitas tersebut bersifat manual, artinya memakai tenaga manusia.
Tipologi kedua, melakukan pengumpulan sampah yang sudah dipilah dalam partai besar, lebel belum dibuang, belum pisah warna dan disebut masih kotor, seperti plastik mainan, PET kotor, aqua (PP) gelas kotor, emberan, dll. Selanjutnya plastik tersebut disortir dalam partai kecil, PET dibersihkan label dan tutupnya, PP gelas dibersihkan tutupnya. Mainan disortir ada PK, Naso, LD, dll, sedang ember dipisah warna. Pemilahan bertujuan meningkatkan nilai jual dan mempermudah proses berikutnya. Sampah plastik tersebut siap giling/cacah dan harganya lebih tinggi ketimbang plastik campuran. Contoh harga PET bersih Rp 4.000/kg dan setelah dicacah bisa mencapai Rp 6.500-7.000/kg.
Tipologi ketiga, ada pengepul yang memperoleh sampah berasal dari kawasan industri/pabrik. Misalnya pengepul dirgen plastik, kaleng, drum (besi dan plastik), pallet, plastik sisa/BS, limbah besi, kardos, dll. Hal ini bisa ditemui di sepanjang jalan Kalimalang Kabupaten Bekasi, jalan Narogong Kota Bekasi, Ciulengsi hingga Gunung Putri Kabupaten Bogor, dll. Ini disebut limbah industri non-B3 yang memiliki nilai ekonomis. Limbah industri non-B3 tersebut jadi rebutan dan dikuasai oleh networking yang kuat dan bermodal besar. Para pemain limbah ini biasanya menaruh deposit ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Tipologi keempat, pengepul untuk kepentingan pencacahan plastik. Aktivitas tersebut membeli berbagai jenis plastik yang telah disortir dalam partai besar. Selanjutnya, plastik tersebut disortir dalam partai kecil siap cacah. Upah sortir Rp 300-500/kg. Biasanya menggunakan sistem borongan. Kalau upah harian untuk lelaki Rp 50.000-75.000 dan perempuan Rp 35.000-50.000. Misalnya, usaha pencacahan ada yang fokus pada PET dan PP gelas, ada yang fokus pada mainan dan emberan, dan ada yang fokus pada himpek dan PVC. Selain itu, ada yang fokus pada pencacahan dan pembekuan styrefoam. Kegiatan ini sudah didukung oleh teknologi mesin pencacah dengan permodalan agak lumayan besar.
Bank sampah dalam konteks tersebut biasanya masuk dalam tipologi pertama dan kedua, jarang yang masuk tipologi keempat. Karena bank sampah menerima penjualan atau setoran dari anggota. Biasanya, sampah organik dikomposkan jadi pupuk organik. Sedangkan sampah an-organik dikumpulkan, seperti plastik, kertas, dll dan dijual ke pelapak terdekat karena kuantitasnya tidak banyak.
Kondisi ini menyebabkan bank sampah tidak bisa berhubungan/kontrak langsung dengan pabrik. Sebab tidak mampu memenuhi target yang diminta pabrikan. Misal, setiap bulan harus menyetor plastik jenis PET dan PP gelas atau kertas 100-200 ton. Namun, ada beberapa bank sampah yang mampu memutar modalnya hingga miliaran rupiah per bulan dan memiliki mesin pencacah plastik.
Memang, sebaiknya berbagai elemen/lembaga, yakni bank sampah, KSM, komunitas pengolah sampah, PDUS, Pusat Olah Sampah 3R, TPS 3R, dll yang melakukan pilah dan olah sampah harus berkolaborasi. Pemerintah harus memperkuat perekat koordinasi, kolaborasi dan kemitraan dalam konteks kebijakan yang memihak, permudah perijinan, permodalan mudah dan cepat, dukungan multi-teknologi, pasar dan informasi daur ulang secara cepat dan tepat.
KPNas, APPI dan YPLHPI sangat mendukung upaya pemerintah membangun Gerakan Nasional Pilah dan Olah Sampah dari Sumber. Dengan slogan pro clean and green: “Pilah dan Olah Sampah dari Sumber KEREN”.
* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)/Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)

 REDAKSI
REDAKSI