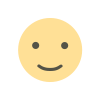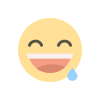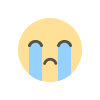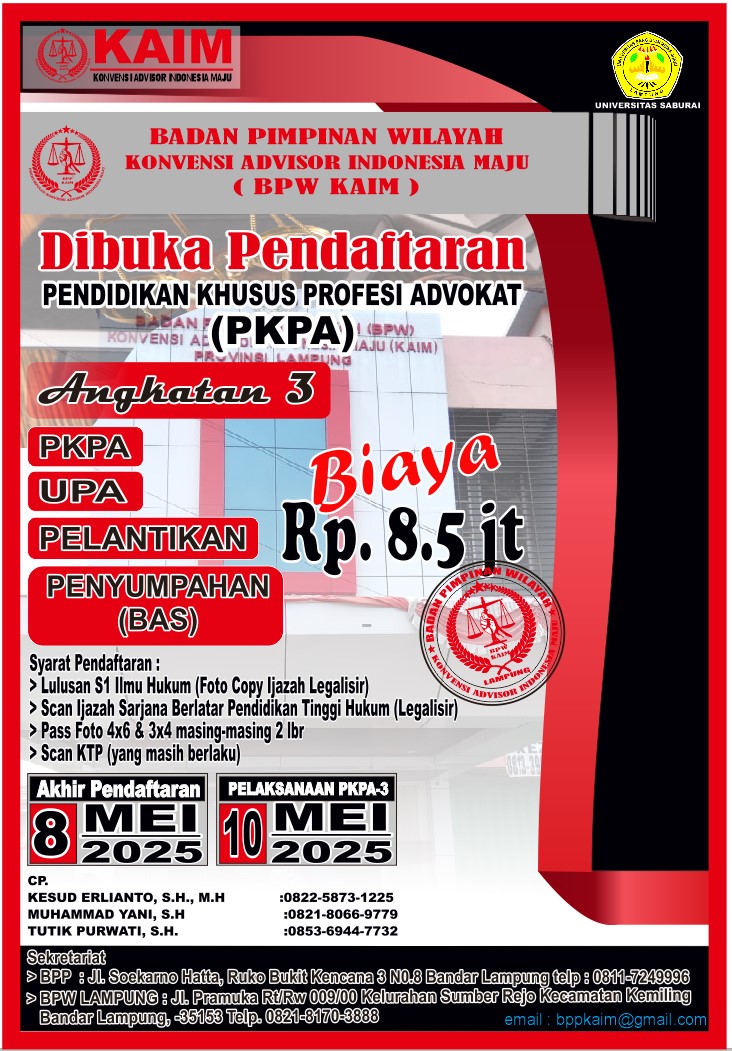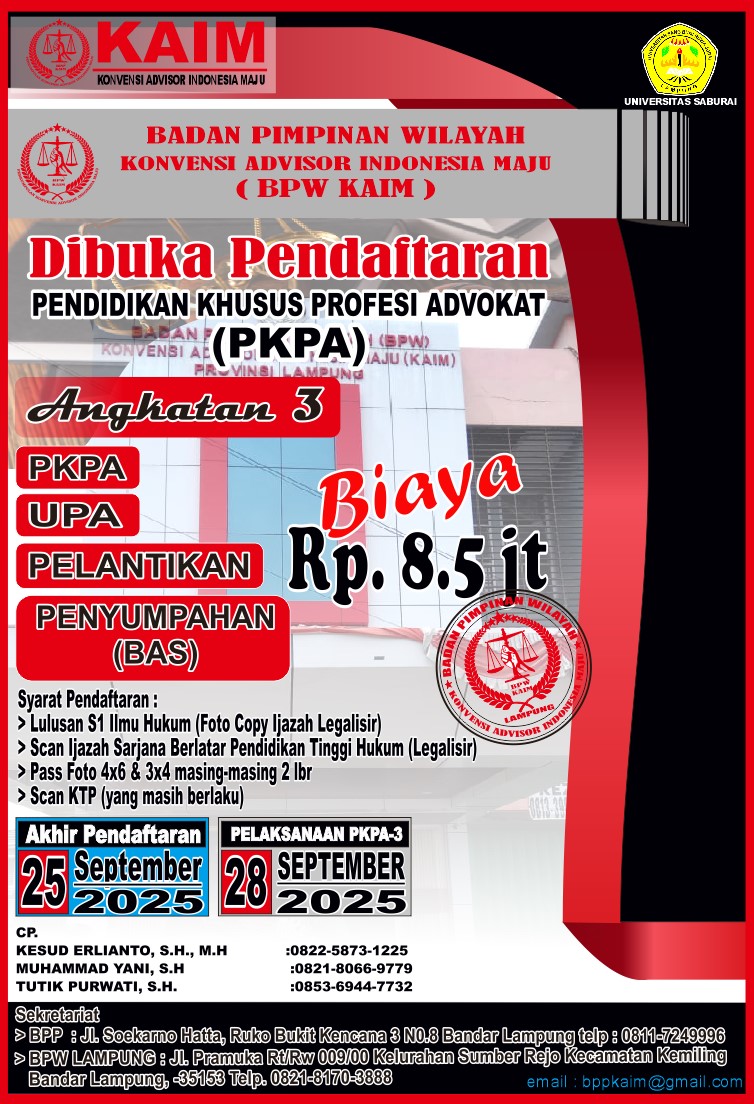Catatan Akhir Tahun 2020: Urusan Sampah dan Pemulung Masih Mengganjal
Oleh: Bagong Suyoto*
KASUS korban COVID-19 meningkat dan malah terjadi mutasi baru akibat longgar terhadap protocol kesehatan WHO. Semakin banyak yang mati. Sejumlah negara berhati-hati dengan varian Corona jenis baru, ada yang bilang lebih ganas, kasusnya menerpa Inggris, sejumlah negara Eropa dan kini sudah sampai di Singapora. Sementara vaksin penangkalnya masih diuji-coba di laboratorium dan orang tertentu.
Peningkatan kasus COVID-19 berdampak pada meningkatnya limbah medis, dimana pada akhir tahun 2020 masih ditemukan di sejumlah tempat, seperti lahan kosong, drainase, DAS, badan sungai, dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Limbah infeksius tidak boleh dibuang ke TPA, apalagi dibuang di sembarang tempat. Hal ini mengidikasikan tata kelola limbah medis masih bermasalah. Hampir semua media ibukota dan lokal serta sejumlah media asing (The Straits Times, CNN, BBC, VOA, dll) melaporkan situasi pengelolan limbah medis yang buruk itu.
Bukan hanya limbah medis, limbah B3, bahkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih bermasalah, malah dalam kondisi darurat sampah. Hal ini dialami kota Yogyakarta, sampah menumpuk di sejumlah titik sejak belakangan TPA Piyungan ditutup warga. Alasan warga menutup TPA karena sampah tak dikelola dengan baik, malah tercecer di badan jalan.
Pengelolaan TPA dengan sistem konvensional, sistem open dumping, paling banter control landfill dilakukan mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. IPAS alakadarnya, bahkan ada yang tak punya IPAS. Air lindi mengalir ke mana-mana mencemari tanah, air permukaan dan air dalam. Bulam lagi pencemaran udara, dibarengi belatung dan koloni lalat semakin banyak. Hal ini diperparah sampah sering longsor pada musim hujan dan terbakar pada musim kemarau. Kondisi buruk ini bisa dilihat TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu, TPA Burangkeng, TPA Cipeucang, TPA Rawakucing, TPA Jatiwaringin, TPA Jalupang, TPA Galuga, dll.
Kondisi buruk itu dialami oleh sejumlah metropolitan, kota besar, bahkan kota kecil. Mereka kesulitan mengelola TPA-nya. Gunung-gunung sampah semakin tinggi, tanpa penataan dan cover-soil yang memadai. Sejenis TPA open-dumping. Mereka masih menerapkan paradigma konvensional. Artinya, belum menjalankan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012. UU tersebut merupakan dasar paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia.
Kita lihat sebagian pusat-pusat kota semakin bersih dari sampah, dengan berbagai pepohonan dan taman-taman sangat indah dan sejuk. Sayangnya, ketika melihat TPA-nya, situasinya sangat menyedihkan sekali. Hampir tiap hari warga sekitar TPA komplin karena bau menyengat dan lalat bertebaran menyerang kampung. Sedang warga lain masa bodoh, sudah bosan mengadu dan memberikan masukan pada pemerintah setempat.
Juga masih ditemui sejumlah titik pembuangan liar di beberapa kabupaten/kota disebabkan rendahnya tingkat pelayan, teknologi pengolah sampah tak tersedia, sementara populasi terus bertambah, gaya hidup konsumerisme, dll. Selain semakin banyaknya pemuangan sampah illegal, sungai pun jadi tong sampah raksasa dan selanjutnya terbawa air ke laut. Sampah yang masuk ke sungai sebagian besar terdiri dari plastik, styrefoam, busa, kasus, karet/ban, berbagai jenis ranting dan pohon besar. Ada yang bilang, sungai jadi permadani sampah!
Sementara orang-orang yang telah berjasa ikut mengurangi, mengguna-ulang dan mendaur-ulang sampah kurang mendapat perhatian pemerintah. Mereka diantaranya, pemulung, buruh sortir, pelapak, tenaga kebersihan, dll. Belum semua pemulung memperoleh bantuan social (Bansos) dari pemerintah selama pandemic COVID-19, padahal mereka sedang kesulitan. Karena harga-harga pungutan sampah jatuh. Misal, harga sampah campuran jatuh, Rp 600-800/kg, ketika kondisi normal mencapai Rp 1.000-1.200/kg.
Sejumlah pemulung, orang kecil dan pekerja di persampahan belum mendapat sentuhan dari pemerintah, malah terdengar petir gemuruh, Bansos dikorupsi oleh Menteri Sosial dan rombongannya, dan juga sejumlah pengusaha pada akhir tahun 2020. Berita ini melukai hati rakyat miskin, pemulung di seluruh Indonesia. Sang Menteri dan kawananya terkena OTT KPK.
Memang orang kaya dan petinggi negara mempunyai gaji dan income cukup besar dan peluang lebih besar, termasuk untuk berbuat korup. Coba lihat dan bandingkan dengan pendapatan pemulung. Pemulung yang kuat, sehat memperoleh pendapatan Rp 100.000-120.000/hari. Sedang pemulung perempuan rata-rata Rp 50.000-60.000/hari. Sedang buruh sortir mendapat Rp 35.000-50.000/hari. Pendapatan pemulung ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dengan menu sederhana. Apalagi kalau pemulung memiliki keluarga besar dengan anggota keluarga 5-6 orang. Kehidupan mereka tetap miskin.
Ketika pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemic, komunitas pemulung pun diabaikan sedemikian rupa tanpa harapan. Pemulung dan tenaga kebersihan tak tersentuh. Suaranya tak terdengar oleh para pengambil keputusan di ibukota. Sampai akhir tahun 2020 pemulung dianggap tidak ada perannya. Alasannya, Menteri Keuangan RI belum menyetujui.
Pemerintah silih berganti belum memberikan penghargaan yang semestinya pada pemulung. Katanya, mereka yang ikut mengelola sampah prinsip 3R akan mendapatkan kompensasi atau insentif seperti dimandatkan UU No. 18/2008. Peran pemulung sudah jelas mengapa diabaikan?
Pemulung Pelaku 3R Sampah
Dalam buku Tri Bangun L. Sony dan Bagong Suyoto, Pemulung Sang Pelopor 3R Sampah (2008) dinyatakan, bahwa pemulung memiliki peranan sangat besar dalam penerapan kegiatan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah atau dikenal dengan 3R (reduce, reuse, recycle). Pada aras internasional lebih populer dikenal 3R. Selama ini kegiatan 3R dipahami hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, khususnya pemerintah. Padahal pemulung telah mengimplementasikan secara riel siang malam tanpa mengenal lelah sejak 1960-an atau 1970-an. Bahkan seluruh keluargannya dilibatkan dalam aktivitas 3R tersebut.
Pantaslah bila kita memberi julukan, pemulung sebagai Sang Pelopor 3R Indonesia. Garda depan 3R di Indonesia. Penyematan simbol ini belum ada yang melakukan. Dalam sejarah pengais sampah tidak langsung disebut pemulung, tetapi Gepeng. Gepeng singkatan dari gelandangan dan pengemis. Dulu kehidupan pengais sampah amat menyedihkan; dikejar-kejar, digusur, dan ditekan sedemikian rupa. “Rumah-rumah liar di Jl. Cacing dirobohkan pakai traktor“, dalam Harian Umum Pos Kota, Kamis, 30 Juni 1988. Harian itu menulis; Penghuni bangunan liar (gubuk pemulung – penulis) di sepanjang Jalan Cacing yang masuk wilayah Jakarta Timur mengaku dikenakan uang bangunan Rp 10.000 dan uang bulanan Rp 1.000. Warga yang kehilangan tempat berteduh di wilayah ini tercatat 115 KK dengan jumlah jiwa 421 orang.
Pengais sampah berjuang agar diakui keberadaanya. Lalu pada 1988 penguasa Orde Baru menganugrahi nama Laskar Mandiri. Artinya pasukan yang memiliki kemandirian, tak bergantung pada siapa pun. Dalam sejarah perjalanan pengais sampah di Indonesia, terutama di ibukota partisipasi mereka sangat jelas dalam kegiatan 3R dan aktivitas turunannya.
Jumlahnya ribuan, bahkan jutaan pemulung yang menambatkan hidup pada sampah. Kegiatan pelopor 3R ini secara langsung dapat income, menciptakan lapangan kerja, membantu meningkatkan kebersihan kota, memperpanjang umur TPA, dan mengembalikan sampah menjadi sumberdaya (return to resouces).
Profil Pemulung
Bagong Suyoto (2006) menyebutkan, di mana ada pembuangan sampah di situ ada pemulung, atau sebaliknya, di mana ada pemulung di situ ditemui sampah. Pemulung memiliki pekerjaan sebagai pengais sampah. Antara sampah dan pemulung bagaikan dua sisi mata uang. Pemulung tidak peduli meskipun hidup di bawah kolong jembatan atau kolong langit yang penting berdekatan dengan tempat pembuangan sampah.
Ada dua jenis pemulung dalam menjalani pekerjaanya. Pertama, pemulung tidak menetap, artinya pemulung yang memungut sampah keliling dari gang-gang kampung, TPS-TPS, taman kota, pinggir jalan, pinggir sungai, dst.
Kedua, pemulung yang mencari sampah menetap, contoh di TPA. Mereka yang mengais sampah menetap dan bermukim di gubuk-gubuk kardos, triplek, seng bekas atau terpal bodol. Keberadaan mereka dapat ditunjukkan pada pemulung di sekitar TPA Bantargebang, TPA Sumurbatu, TPA Nambo Bintang, TPA Muara Fajar, TPA Rawa Kucing, TPA Benowo, dan TPA lain di seluruh Indonesia. Pada umumnya kondisi gubuk-gubuk pemulung sangat menyedihkan, kumuh dan berada pada lingkungan tercemar.
Pemulung yang menetap di kisaran TPA dibagi menjadi dua. Pertama, pemulung yang menggantungkan hidupnya seratus persen pada sampah. Kedua, ada pemulung yang melakukan kegiatan ini setelah tanam atau memanen padi atau palawija di kampungnya. Sembari menunggu musim panen, mereka mengis sampah. Jadi tipe pemulung tersebut memiliki pekerjaan di sektor pertanian dan sampah.
Beberapa alasan menjadi pemulung. Pertama, tidak ada pilihan lain karena bangkrut usaha atau sedang cari kerja. Kedua, diajak bos, saudara atau tetangga yang telah berhasil secara materi. Ketiga, meniru teman atau tentangga yang sukses dari sampah. Keempat, menunggu masa tanaman panen.
Sekarang jumlah pemulung di sekitar TPA Bantargebang dan TPA Sumurbatu diperkirakan 6.000 orang. Dari jumlah tersebut separohnya adalah pendatang, yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dll. Moyoritas asal pemulung dari Indramayu, Kerawang, Subang, Cerebon, Bekasi Utara, Semarang, Solo, Surabaya, Pasuruan, Madura.
Berbagai etnis berbaur dan beranak pinak di lingkungan TPA, seperti miniatur bangsa Indonesia. Mereka berinteraksi dalam bisnis maupun kekerabatan. Bahkan diantara pemulung pendatang melakukan akulturasi dengan penduduk asli sekitar TPA, misal dengan melakukan perkawinan antar suku.
Dalam segi kemasyarakatan, pemulung memberikan kontribusi atas pembangunan wilayah yang didiami, seperti iuran keamanan, gotong royong, kegiatan sosial keagamaan, olah raga, dll. Upaya ini dilakukan agar keberadaan pemulung diterima secara luas di sini. Pemulung telah berbuat untuk masyarakat dan dirinya sendiri.
Pemulung Jadi Korban
Pemulung tidak mendapat jatah uang bau, tipping fee, asuransi kesehatan, ruang kerja yang layak, dst. Posisinya selalu jadi korban ketika terjadi malapetaka sampah. Korban dari kebijakan yang tidak pro-kemanusiaan. Kita sebaiknya menempatkan posisi pemulung pada aras yang semesetinya, sebab mereka telah berbuat untuk kita. Pemulung rela membersihkan kotoran orang lain. Tidak ada manusia yang seheroik pemulung.
”Mungkin belum pernah lebih penting daripada sekarang untuk mengatakan apa yang mitos katakan: bahwa humanisme yang teratur tidaklah dimulai dari dirinya sendiri, tetapi mengembalikan hal-hal pada tempatnya. Dia menempatkan dunia di depan kehidupan, kehidupan di depan manusia, dan penghormatan kepada yang lain di depan cinta diri. Inilah pelajaran yang oleh orang-orang yang kita sebut ”Orang biadab” ajarkan kepada kita: pelajaran tentang kerendahan hati, kesopanan dan kebijaksanaan di hadapan dunia yang mendahului spesies kita dan akan mempertahankan kehidupannya”. Demikian dikutip dari Claude Levi-Strauss dalam “A Short of Pope”, Psycology Today (1972).
Bagong Suyoto (2007) menulis, memang sangat sulit memberikan penghargaan kepada pemulung, suatu elemen di dalam masyarakat Indonesia atau di belahan dunia lain yang memiliki pekerjaan mengais sampah. Pemulung berkerumun memperebutkan sampah di bawah cakar-cakar excavator. Sekali lengah digilas atau dicakar mesin raksasa itu. Ancaman bachoe, buldozer hingga beling atau paku menghantui setiap saat. Nasib naas ... kematian menyosong pemulung. Jika tidak, bahaya titanus atau cacat seumur hidup. Oh, pemulung dalam ujung tanduk kehidupan. Sudah berapa puluh pemulung yang cacat dan tewas akibat tergilas alat-alat berat.
Pada awal Maret 2006 lalu terjadi kecelakaan pada seorang pemulung, tergolong masih muda. Ia berusaha merangsek mangais sampah di belangkan buldozer. Tak disangka buldozer itu mundur menggilas kaki dan separoh badannya. Lalu, pemulung dipapah dibawa ke Puskesmas Bantar Gebang. Pihak TPA Sumurbatu, cuma memberi bantuan Rp 500.000. Karena minimnya uang ia tak sanggup membayar perawatan dokter hingga sembuh, akhirnya pemulung itu dipulangkan ke kampung halamannya, Babelan Bekasi Utara. Mustahil pemulung itu dapat pulih seperti sedia kala.
Pemulung lain nasibnya nyaris serupa. Masih ingkatkah kasus Supriono? Supriono adalah pemulung yang tinggal bersama anaknya. Ia telah bercerai dengan istrinya. Khaerunis (3 tahun) anaknya sakit dan sekali dibawa ke Puskesmas. Pada 5 Juni 2005 sekitar pukul 07.00 anaknya meninggal dalam gerobak pemulungnya, yang sedang mangkal di Manggarai, Jaksel. Supriono membawa mayat anaknya dengan gerobak ke stasiun kereta api Tebet, ditemani anak pertamanya, Muriski Saleh (6 tahun). Dengan maksud akan membawa jenazah itu ke Bogor. Namun saat menggendong mayat anaknya dengan tutup kain kumal diketahui banyak orang. Pemulung itu dilaporkan ke polisi. Malangnya ia tidak ditolong malah diinterogasi dan lalu ia diminta membawa mayat anaknya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumu (RSCM). Dengan perasaan sedih Supriyono diperlakukan sangat tidak simpati. Entah bagaimana, pemulung ini bisa membawa dan menguburkan mayat anaknya di Bogor. Kisah tragis seorang pemulung di abad MDGs.
Bagi pemulung menghadapi kematian dan menuju tanah penantian pun dihambat oleh mesin-mesin kekuasaan. Ada kecurigaan mendalam atas keberadaan pemulung, gembel gelandangan, kaum miskin kota. Pemulung adalah manusia bukan hantu belang.
Bagong Suyoto (2005) mencatat, ratusan pemulung menjadi tumbal meledak dan longsornya TPA Leuwigajah, Kota Cimahi/ Bandung, Jawa Barat. Tragedi TPA Leuwigajah itu sampah benar-benar “membunuh” ratusan manusia dan menghancurkan rumah, ternak, dan segala yang ada di atasnya pada akhir Februari 2005. Wilayah yang paling parah adalah RW VIII dan RW IX Kampung Cilimus, Desa Batujajar Timur, Kabupaten Bandung serta RW XIII Kampung Pojok, Desa Cirendeu, Kota Cimahi.
Sampah longsor akibat pengelolaannya yang sembrono, tidak berpijak pada SOP atau standar-standar internasional. Setidaknya 181 jiwa tewas, 17 orang masih tertimbun sampah, ratusan rumah lenyap tertimbun sampah. Ada yang mengatakan, data korban tewas sebanyak 200 orang. Mereka masih hidup menanggung trauma.
Tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah belum reda, menyusul bencana sampah longsor di TPS Lembah Ampera Lembang, Kabupaten Bandung. Sebanyak 6 rumah hancur dan menelan korban 2 jiwa. Sampah membawa petaka.(Bagong Suyoto, 2007).
Bagong Suyoto (2007) menyebutkan, pemulung juga menjadi korban sampah longsor di Zona III TPA Bantargebang. TPA Bantargebang seluas 108 hektar milik DKI Jakarta itu dikelola dengan sistem quasi-open dumping. TPA itu dikelola pihak ketiga, yaitu PT PT PBB sejak tahun 2004. Sayangnya PT PBB mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berkali-kali sepajang tahun 2006 TPA ini diguncang oleh berbagai demo massif baik dari dalam maupun luar. Akibat ketidakbecusan mengelola sampah di TPA tersebut ujung-jungnya sampah longsor dan menelan korban nyawa.
Ratusan orang dari wilayah kisaran TPA Bantargebang maupun dari Jodetabek datang melihat langsung peristiwa tragis itu. Tiga hari berturut-turut tempat itu tak pernah sepi dari manusia. Polisi, tentara, satpol, SAR, kalangan pemerintah dan lain-lain menjaga dan ikut melakukan evakuasi. Pihak DKI Jakarta pun menurunkan Satpol PP. Sebanyak 6 hingga 7 backhoe, 2 buldozer, dan beberapa truk sampah dikerahkan untuk mengangkat sampah yang longsor dari teras 4 (paling atas), 3, 2 dan 1. Longsoran sampah menerjang badan jalan kampung di wilayah RT 03/RW Kelurahan Ciketingudik.
Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat dini hari, 8 September 2006 lalu. Jumat dini hari, atau Kamis malam Jumat menjadi hari yang naas bagi pemulung yang sedang mengais sampah. Menurut penuturan sejumlah pemulung, ketika sampah longsor lebih dari 50 pemulung sedang istirahat sembari menikmati kopi dan teh hangat atau makan supermie instant pada warung-warung kecil yang berjajar di tepi zona III tersebut. Sedangkan pemulung lain ada yang mengais sampah secara bergerombolan. Demikian juga ada alat berat yang beroperasi karena ada truk sampah yang datang dan truk lainya akan pergi.
Sementara itu beberapa warung kecil yang berada di bawah hancur tergulung sampah. Sebagian pemulung dapat melarikan diri, lainnya terseret sampah masuk kedalam saluran lindi bercampur sampah dan terluka. Kedalaman air leachet kali itu lebih dari 1,5 meter. Tiga tiang listrik roboh dan patah. Puluhan gerobak dan keranjang pemulung ikut tergulung sampah dan masuk ke dalam kali/saluran air. Gerobak-gerobak pemulung itu hancur, roda-rodanya terpisah dari baknya. Juga ada satu truk sampah yang terlempar ke selatan pinggir kali, dan bodinya hancur. Menurut warga truk sampah tersebut dipotong-potong karena ada korban yang terjepit truk sampah tersebut. Korban berada di dasar kali leachet dan tergencet truk sampah.
Demi Mempertahankan Hidup
Siang malam mengorek sampah, rasa capek menyayat, lalu tidur lelap di gubuk kardos atau triplek bekasnya. Pagi hari bangun, di depannya sampah berserakan. Air lindi mengalir di sekeliling gubuknya. Bau bacin tengik bak tahi belincung menebar menembus udara siang malam tanpa batas. Pemulung hidup di tengah-tengah lingkungan yang tercemar. Perkara lingkungan tak mengenal batas teritorial. Sampah orang Bogor yang dibuang ke Sungai Ciliwung terbawa derasnya air sampai ke Jakarta, dan sampah pun menjadi masalah Jakarta. Kemudian masuk Teluk Jakarta, ke perairan Kepulauan Seribu dan akhirnya menyebar ke Laut Jawa. Demikian juga udara busuk sampah menyebar tidak sebatas di kisaran TPA Bantargebang saja, namun hingga puluhan meter, seperti Klapanunggal Bogor, Villa Nusa Indah Gunung Putri, dll.
Pemulung meminum air yang tercemar virus coli, sejenis senyawa tinja. Juga tercemar logam berat, termasuk sianida, amoniak, timbal (Pb), kadmium (Cd), seng (Zn), besi (Fe), dan lainnya. Mereka tak mempedulikan jiwanya, yang penting bisa bertahan hidup. Mereka pasrah dalam keterpaksaan kejamnya dunia. Pencemaran adalah ancaman pembunuhan yang tidak kasat mata, namun pasti. Mereka dalam gerbang maut, yang dipahami dalam desisan nafas dan detak jantung.
Pemulung merupakan bagian warga negara ketahanan panganya sangat ringkih. Pemulung berusaha mempertahankan pangannya dengan cara mengais sisa-sisa makanan di TPA. Menu makan sehari-hari sangat sederhana. Pemulung makan nasi pera, beras Rp 1.000/Kg dengan lauk ikan gesek (ikan asin dengan pengawet formalin). Ada sayur asem dari cecek, daun mlinjo dan labu. Sekarang harga beras pera ikut meroket, seperti BBM, Rp 2.400 – 3.000 /Kg.
Dalam buku Bagong Suyoto, Bluweng: Mencari Mesias di Tengah Gunungan Sampah (2006) disebutkan, Pemulung perempuan atau lelaki memungut untuk kebutuhan makan mereka, seperti sisa daun sawi, kacang panjang, nangka muda, wortel, kol, kangkung, bayam, sisa ikan asin atau pindang, sisa daging ayam, dan lain-lain. Ada yang bilang, mengais dan memakanan sisa-sisa dari sampah adalah kenistaan yang sulit dijabarkan dengan akar keagamanan. Kelompok agama ini memandang, jenis makanan itu penuh najis dalam berbagai tingkatkan najis (jika dimakan hukmnya haram). Makanan dari sampah bukan hanya sudah jadi bangkai. Mereka tak termaafkan oleh kemuliaanya sendiri. Disini tidak ada keterpaksanaan, bahwa setiap hari orang diperbolehkan mengeyam sisa makanan dalam sampah. Yang dimaksud terpaksa adalah tak ada pilihan lain? Namun, apa gunanya memperdepatkan nilai-nilai yang dianggap tropan ini. Manusia telah lari dari sesuatu yang dianggap sakral.
Implikasi langsung dari pemulung dewasa mengais sisa makanan, sangat jelas, dibawa pulang, sampai digubuk dimasak dan lalu dimakan bersama-sama. Ana-anak pun ikut menikamati lezatnya sisa makanan dari sampah. Anak-anak tak pedulikan dari mana asal usul makanan yang diperoleh orangtuanya. Yang penting ada di meja makan, disajikan di depannya. Apalagi makanan yang telah dimasak itu mengeluarkan rasa harum, atau sejenis bau ikan goreng atau ayam goreng. Ketika perut sudah melilit selera makan anak-anak tak lagi bisa dikekang. Dengan rasa merintih, mak minta makan. Puluhan bahkan ratusan anak-anak pemulung miskin terancam kekurangan gizi. Siapa yang peduli dengan pemulung miskin, kelompok Gepeng itu?
Inikah cara hidup pemulung, mengais sisa-sisa makanan dari hamparan sampah di TPA Bantargebang dan Sumurbatu. Selain mengorek sampah, mereka juga menyisihkan waktu memungut sisa-sisa makanan. Tidak ada selera yang bisa diukur dari sini, kecuali orang memiliki pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Tidak mudah menafsirkan perilaku pemulung mengais sisa makanan dari sela-sela tumpukan sampah. Hanya komunitas pemulung yang dapat memahami. Hanya mereka yang bergumul dengan pemulung yang dapat menempatkan perilaku pemulung ini dalam suatu perilaku survival of the fites.
* Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
*Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

 REDAKSI
REDAKSI