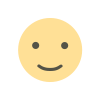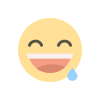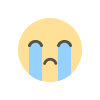Stabilitas Semu Pasar Keuangan Indonesia: Distorsi Likuiditas dan Pengorbanan Sektor Riil

Oleh : Arief Poyuono *)
Dalam khazanah ekonomi modern, terdapat satu prinsip fundamental yang relatif tak terbantahkan, bahwa pasar keuangan yang sehat semestinya berfungsi sebagai refleksi nilai fundamental ekonomi sekaligus sebagai mekanisme transmisi yang efisien, menyalurkan tabungan menuju investasi produktif. Ketika pasar keuangan tumbuh pesat sementara sektor riil stagnan, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan distorsi.
Fenomena inilah yang secara mencolok muncul dalam perekonomian Indonesia pada kuartal terakhir tahun 2025. Di satu sisi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus level 8.600. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 %, konsumsi rumah tangga melemah, dan investasi belum sepenuhnya pulih pasca-guncangan global beberapa tahun terakhir.
Ketimpangan antara euforia finansial dan realitas ekonomi ini menandai sebuah paradoks yang serius, yakni pemutusan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil, sebuah decoupling yang berbahaya.
Paradoks tersebut semakin tajam ketika mencermati komposisi arus modal asing. Pada awal Desember 2025, sekitar 77 % dari total inflow asing justru terserap oleh Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara pasar saham memperoleh porsi yang relatif kecil. Artinya, modal asing yang masuk ke Indonesia tidak ditujukan untuk membiayai ekspansi korporasi, inovasi industri, atau penciptaan lapangan kerja, melainkan untuk parkir sementara pada instrumen jangka pendek yang aman dan likuid.
Fenomena ini kerap dirayakan oleh otoritas sebagai “vote of confidence” investor global. Namun, interpretasi semacam itu terlalu simplistik dan mengabaikan dinamika struktural yang lebih dalam. Yang terjadi sesungguhnya bukanlah kepercayaan terhadap prospek produktivitas Indonesia, melainkan manifestasi lokal dari limpahan likuiditas global pasca-normalisasi moneter, di mana modal internasional kembali berburu imbal hasil di pasar negara berkembang.
Kerangka pemikiran Robert Shiller mengenai irrational exuberance memberikan lensa analitis yang relevan untuk membaca reli IHSG. Kenaikan indeks yang tampak impresif tersebut sesungguhnya sangat terkonsentrasi pada segelintir saham berkapitalisasi besar – terutama sektor perbankan, komoditas, dan konsumsi – sementara ratusan emiten lain menunjukkan kinerja yang biasa-biasa saja.
Reli ini lebih mencerminkan dorongan likuiditas portofolio jangka pendek dibandingkan perbaikan fundamental yang merata. Modal global masuk ke Indonesia bukan karena terpesona oleh lonjakan produktivitas atau terobosan teknologi, melainkan karena selisih suku bunga yang menarik dan ekspektasi stabilitas nilai tukar.
Dalam kondisi seperti ini, pasar saham berhenti berfungsi sebagai barometer kesehatan ekonomi dan berubah menjadi semacam spons yang menyerap kelebihan likuiditas global.
Konsekuensinya adalah asset price inflation yang bersifat sempit dan timpang. Wealth effect yang tercipta hanya dinikmati oleh investor institusional, pemodal besar, dan pemegang aset finansial, sementara mayoritas masyarakat – yang penghasilannya bergantung pada upah riil dan kesempatan kerja di sektor riil – tidak merasakan manfaat signifikan.
Hyman Minsky akan menyebut kondisi ini sebagai fase speculative finance, di mana nilai aset lebih ditentukan oleh ekspektasi keberlanjutan arus modal ketimbang oleh arus kas masa depan dari aktivitas produktif.
Sisi lain dari fenomena ini tercermin pada melonjaknya minat investor terhadap SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang dipertahankan pada level relatif tinggi demi menjaga stabilitas rupiah, instrumen-instrumen negara menawarkan imbal hasil riil yang menarik di tengah ketidakpastian global.
Dari sudut pandang teori portofolio, perilaku ini sepenuhnya rasional, dimana investor memilih instrumen berisiko rendah dengan return kompetitif. Namun, rasionalitas mikro ini justru melahirkan disfungsi makro. Joseph Stiglitz telah lama mengingatkan bahwa kemudahan pembiayaan defisit melalui pasar keuangan dapat menciptakan moral hazard fiskal. Ketika pemerintah terbiasa memperoleh pembiayaan murah dan mudah, disiplin fiskal jangka panjang cenderung tergerus.
Dalam konteks Indonesia, gejala ini terlihat dari meningkatnya beban pembayaran bunga yang menggerus ruang fiskal. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak terus membesar, membatasi kapasitas negara untuk membiayai belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Negara berisiko terjebak dalam siklus pembiayaan yang tidak sehat: berutang untuk menutup kewajiban bunga masa lalu, alih-alih berutang untuk membiayai investasi yang menghasilkan pertumbuhan masa depan. Stabilitas fiskal jangka pendek dibeli dengan pengorbanan fleksibilitas fiskal jangka panjang.
Distorsi paling serius justru muncul pada fungsi intermediasi perbankan, sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai “Crowding Out 2.0”. Berbeda dengan teori crowding out klasik yang menekankan kenaikan suku bunga akibat pembiayaan defisit pemerintah, versi modern ini bekerja melalui distorsi insentif. Ketika perbankan dapat memperoleh imbal hasil stabil dan hampir tanpa risiko dengan menempatkan dana pada SRBI atau SBN, dorongan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif melemah. Mengapa bank harus menanggung risiko kredit industri manufaktur atau UMKM, jika instrumen negara menawarkan return yang menarik dengan jaminan implisit dari negara?
Akibatnya, fungsi intermediasi, yang merpakan jantung dari sistem keuangan, menjadi tumpul. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto berjalan lamban, sementara sektor manufaktur mengalami apa yang dapat disebut sebagai deindustrialisasi diam-diam.
Industri yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk modernisasi mesin dan riset kalah bersaing dalam memperebutkan modal. Biaya dana bagi sektor riil tetap tinggi karena perbankan mempertahankan spread yang lebar, sementara suku bunga acuan bertahan tinggi demi menjaga daya tarik aset finansial. Inilah paradoks kebijakan yang menyakitkan, dimana stabilitas nominal sektor keuangan dicapai dengan mengorbankan vitalitas sektor riil.
Lebih jauh, stabilitas yang tampak kokoh ini sangat bergantung pada faktor eksternal yang rapuh, yakni selisih suku bunga global dan sentimen risiko internasional. Selama bank sentral negara maju bersikap relatif dovish, aliran modal ke instrumen carry trade seperti SRBI akan terus mengalir.
Namun, fondasi ini rapuh. Guncangan geopolitik, resesi global, atau perubahan tajam sikap moneter dapat dengan cepat memicu pembalikan arus modal. Dalam skenario tersebut, rupiah akan tertekan, inflasi meningkat, dan Bank Indonesia akan dihadapkan pada trilemma klasik antara mempertahankan stabilitas nilai tukar, menjaga pertumbuhan, atau menguras cadangan devisa.
Situasi ini bukanlah jalan buntu, melainkan sinyal perlunya koreksi kebijakan yang lebih berani dan visioner. Fokus kebijakan harus bergeser dari pengelolaan indikator nominal menuju penguatan fundamental ekonomi.
Kebijakan moneter perlu dilengkapi dengan instrumen makroprudensial yang lebih tajam untuk mengarahkan likuiditas ke sektor produktif. Kebijakan fiskal harus lebih disiplin dan produktif, memastikan bahwa setiap tambahan utang dikaitkan dengan proyek berdaya ungkit tinggi terhadap produktivitas. Pada saat yang sama, reformasi struktural sektor riil – mulai dari deregulasi, kepastian hukum, hingga penguatan inovasi – menjadi prasyarat mutlak.
Pada akhirnya, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis, yakni melanjutkan stabilitas semu yang ditopang modal panas, atau membangun fondasi pertumbuhan yang berbasis produktivitas dan inovasi. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah mereka yang berani melakukan transisi menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Tanpa pergeseran fokus dari manajemen likuiditas menuju pembangunan kapasitas produksi, reli di layar pasar keuangan akan tetap menjadi ilusi.., mengilap, tetapi rapuh.
*) Arief Poyuono: Komisaris PELINDO

 REDAKSI
REDAKSI