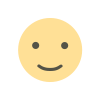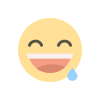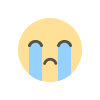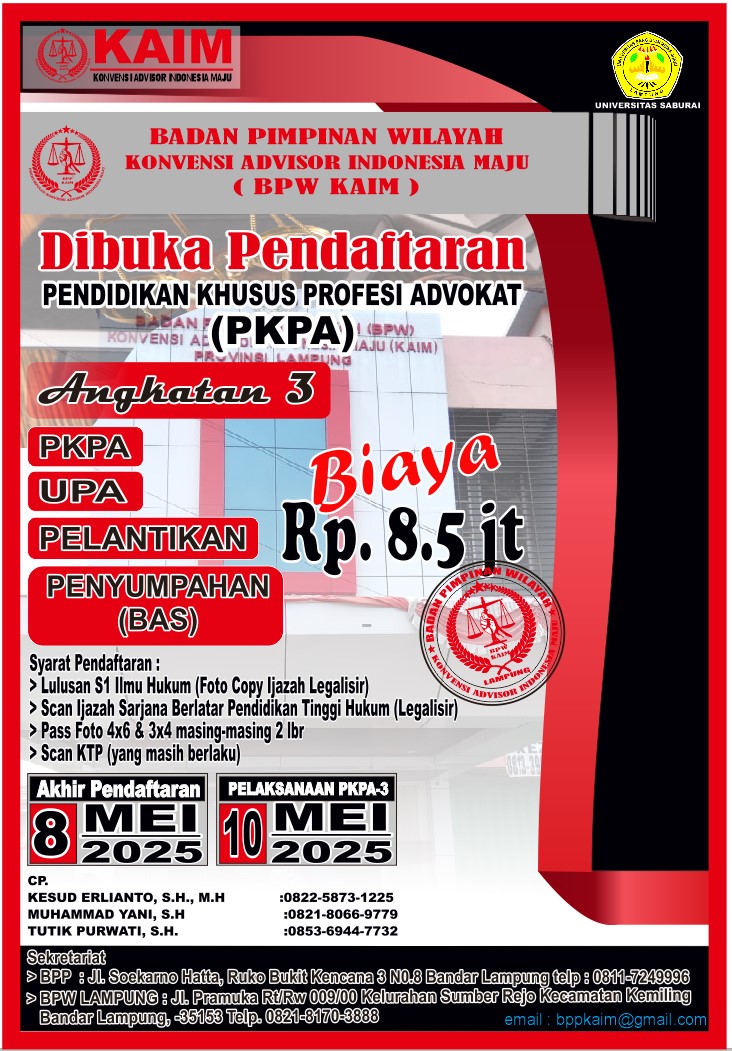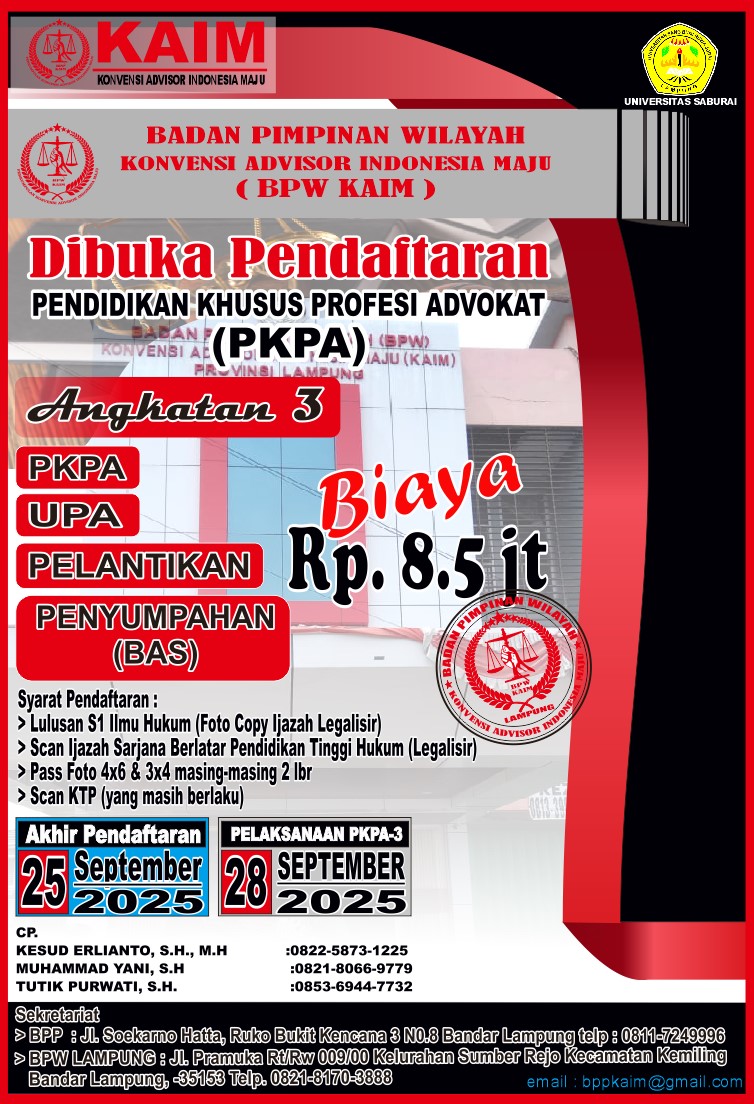Perguruan Tinggi Sebagai Par Excellence Dibelenggu Oleh Hegemoni Kekuasaan
Oleh: Bagong Suyoto*
EROSI dan kejatuhan perguruan tinggi sebagai par excellence disebabkan terutama oleh hegemoni politik praktis dan kekuasaan yang semakin rakus. Dulu, kebebasan kampus diperjuangan dengan pengorbanan sangat besar, bayarannya tindakan represtif dan dikerja-kejar, penjara, penjara, dan kematian. Rezim otoriter melindas kebebasan, meskipun hanya bersuara, suara itu bisa datangnya dari kampus, bisa juga dari forum kritis, seperti kelompok studi mahasiswa, unitas kampus, dll.
Zaman dulu, zaman Orde Baru dimana masih terjadi Dwi Fungsi ABRI boleh dibilang hampir semua kekuatan diratakan bak pasir di pantai. Juga, kekuatan hegemoni kekuasaan menciptakan seragamisasi dari pusat hingga pelosok-pelosok kampung. Suara pun harus sama, kuning atau loreng. Bertahun-tahun rakyat Indonesia, apalagi kampung sulit untuk mengatakan “tidak”. Tidak terhadap kebijakan dan sistem kekuasaan yang tirani dan otoriter.
Keterlibatan dan intervensi militer masuk ke berbagai bidang pembangunan dan kehidupan rakyat semakin kuat. Negara, pemerintah dan penguasa menjadi begitu sangat perkasa. Demikian pula dalam menikmati kue-kue pembangunan. Mereka mengeruk hasil bumi, sumber daya alam, menjual hutan, memonopili berbagai komoditas utama, seperti pemilik Indonesia yang sah. Hal ini dikupas dalam buku Harold Crouch, The Indonesian Army in Politic. Ph.D thesis, Monash University (1975), The Army and Politics in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1978), Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, Asian Studies Association of Australia, 1987).
Situasi itu lama berlangsung, bisa dibilang mulai Orde Lama, sehingga seorang Presiden ingin berkuasa lebih lama, lebih lama lagi, tidak cukup hanya 5 tahun, tambah 5 tahun lagi, sudah 10 tahun. Ada lagi ingi tambah berkuasa 5 tahun lagi. Dan, yang menghentak dunia adalah ingin berkuasa selamanya sampai ajal menjemput. Ini bahaya demokrasi yang luar biasa! Dan ini yang dimaksud “kekuasaan cenderung curang”. Tabiat ingin berkuasa selamanya itu bukan masalah militer atau sipil. Ada sipil berkuasa lebih bengis ketimbang militer, meskipun model-model hegemoninya sangat halus.
Rakyat Indonesia, terutama yang dipelopori mahasiswa dan para aktivis Indonesia ingin merubah menjadi negara demokrasi. Sebab mahasiswa bagian agen perubahan. Bertahun-tahun mereka menentang kekuasaan otoriter. Dan menjadi parlemen jalanan. Pada era 1986/1987-an jika ada mahasiswa yang berani demo, protes di jalan, di depan kantor pemerintah, apalagi ke gedung MPR RI dianggapnya mahasiswa gila, atau bentuk kenakalan pemuda. Saat itu orang demo terhadap kekuasaan dianggap aneh, atau terlalu berani. Karena resikonya sangat besar, bisa tubuh/jiwa melayang.
Ketika itu demo-demo di negeri ini dipelopori mahasiswa dari Malang (Universitas Brawijaya), Surabaya, Yogyakarta (UGM), Jakarta (Unas), Bandung (ITB), dll pada mulanya berawal akibat kekangan ketat terhadap kebebasan kampus. Kemudian menjalar pada dampingan, yakni rakyat dan petani yang tanahnya “dijarah” oleh orang-orang berkuasa, seperti kasus Blangguan, Jatiwangi, Rancamaya, Badega, dll. Dari kasus tanah itu ada yang saya tulis berjudul “Penindasan di Bumi Bebas yang Malang – Kasus Tanah Jatiwangi (Bagong Suyoto, Elsam, 1997). Beberapa kali saya datang dan tinggal di Jatiwangi. Petani Jatiwangi beberapa kali malakukan demo mulai dari ibukota kabupaten, Majalengka hingga Jakarta, terutama Kementerian Dalam Negeri.
Demontrasi itu membara menjadi api besar sekali mengepung gedung MPR RI, dan pada suatu titik klimaks akhirnya Presiden Suharto menyatakan mengundurkan diri di tahun 1998. Kemudian lahir, apa yang dikenal dengan terma “Reformasi”. Dalam perjalanannya sejak titik sejarah reformasi itu sampai detik ini, sudah berganti beberapa presiden. Namun, secara empiris dapat dikatakan reformasi itu kurang total, “Reformasi Setengah Jadi”. Ada sejumlah beban yang tidak diselesaikan secara tuntas. Karena para penguasa yang dulu masih ikut sangat setia berkuasa dan hanya berganti baju. Mereka sembunyi-sembunyi dan malu mengatakan bagian dari Orde Baru. Kenapa malu? Ya, karena ingin tetap berkuasa ingin menikmati uang negara.
Reformasi tersebut sebenarnya berada pada masa transisi. Transisi yang dimaksud adalah interval (selang waktu) antara rezim politik dan rezim yang lain. Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter (1993) lebih senang menyebut rezim baru terbentuk, apa pun corak dan tipenya.
Konteks pembukaan transisi, Philippe Schmitter, Laurance White-head, dll menyatakan, konteks yang paling sering melatarbelakangi dimulainya transisi dari pemerintah otoriter beberapa dekade belakangan adalah kekalahan militer dalam konflik yang bersifat internasional. Lebih jauh, faktor yang paling mungkin mendorong lahirnya hasil demokrasi dari masa transisi adalah penaklukan oleh suatu kekuatan asing yang memang menganut demokrasi politik. Itu untuk kasus negara-negara Pisang, Amerika Latin. Bisa juga, karena rakyat sudah terlalu jenuh dan bosan pada suatu rezim otoriter represif yang berkuasa terlalu lama dengan penuh korupsi. Faktor dorongan internal/dalam negeri merupakan kunci utama perubahan itu.
Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter (1993) lebih jauh mengatakan, situasi transisi dapat digambarkan, bahwa rezim otoriter tertentu menuju “sesuatu yang lain”, yang tidak pasti. “Sesuatu itu” bisa jadi pemulihan suatu demokrasi politik, atau restorasi bentuk baru – yang mungkin lebih buruk – rezim pemerintah otoriter. Hasilnya mungkin hanya kekisruhan, yakni penggiliran kekuasaan diantara serangkaian pemerintahan yang gagal menyodorkan alternatif pemecahan yang dapat bertahan atau dapat diramalkan bagi masalah pelembagaan kekuatan politik. Transisi juga dapat sebagai perkembangan menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan draktis dari kenyataan politik yang ada.
Dunia kampus, para aktivis, rakyat, dll ingin demokrasi ditegakkan, kebebasan bicara dijamin sebagaimana mandat UUD 1945. Sayangnya, kekuasaan dan pemerintah tampaknya kurang senang kebebasan dan demokrasi berkembang. Berbagai UU dan peraturan pemerintah diproduksi guna mereduksi kebebasan dan demokrasi. Bahkan, dunia kampus pun digenggam oleh hegemoni kekuasaan, suatu penaklukan melalui kebijakan dan peluang-peluang untuk berpolitik praktis, seperti pemberian jambatan kominisaris atau lainnya pada rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Statuta universitas pun dirombak demi melemahkan kampus.
Kampus sebagai par excellene merupakan pusat keunggulan, bukan menara gading. Perguruan tinggi mempunyai suatu sumpah, tekad atau amanah yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan utuh. Itulah yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Tridhrama berasal dari Bahasa Sansekerta, artinya tiga ajaran kebenaran. Yaitu pendidikan tinggi harus menjalankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UU No, 12/2012, yang sebelumnya tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Guna menjalankan Tridharma perguruan tinggi tersebut masih banyak tantangan dan hambatan, diantaranya sarana dan prasarana kurang memadai, kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan belum optimal, manajemen perguruan tinggi belum tertata dengan baik, kualitas masih kurang. Hal ini diperparah adanya keinginan dan upaya-upaya pemerintah memberangus iklim kebebasan di kampus. Dan di era pemerintah sekarang tampaknya sudah berhasil mengendalikan perguruan tinggi. Kebebasan kampus pada titik nadir! Ini sangat berbahaya bila berlanjut!?
Dulu, gerakan mahasiswa dilindungi dan diayomi oleh birokrat kampus, seperti dikatakan ekonomo senior UI, Faisal Basri. Contoh, kejadian pemanggilan BEM UI oleh rektorat untuk menghapus julukan King of Lip Service baru kali pertama terjadi. (RMO.ID, 2/7/2021).
“Dulu kita menulis, mengkritik pemerintah, perusahaan, pihak kampus sama sekali tidak pernah intervensi karena ada kebebasan intelektual. Kalau sekarang kan yang ngangkat rektor UI adalah birokrat, teknokrat, dan konglomerat,” kritiknya.
Ambivalensi Universitas dan Negara. “Banyak dosen dan mahasiswa dihukum karena mengajukan protes. Kebebasan akademik Indonesia jatuh ke titik nadir. Kenapa?” (Robertus Robert dalam Tempo, 11/9/2021). Dunia akademi Indonesia sedang mengalami kemerosotan parah. Berita-berita hari ini menebalkan kecemasan bahwa kebebasan akademi universitas kita sedang rapuh, melorot, bahkan ambruk.
Dosen Universitas Syah Kuala Aceh, Saiful Mahdi, masuk penjara hanya karena menulis pesan sederhan di group WhatsApp fakultasnya. Seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ramsiah Tasruddin, dilaporkan ke polisi karena mengkritik kampusnya. Ramsiah menjadi tersangka pencemaran nama baik dijerat UU ITE akibat dilaporkan oleh mantan Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar Nur Syamsiah. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi perkara pencemaran nama yang menjerat Saiful Mahdi. Putusan itu dianggap melampui norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kebebasan kampus jatuh di titik nadir adalah fakta hari ini, merupakan isyarat dan fakta empiris kita tidak mampu mencetak generasi yang cerdas, kreatif, inonatif dan mandiri. Merupakan wadah mencetak produk unggul, par excellence. Dalam sejumlah penilaian oleh lembaga survey internasional, kualitas produk dan perguruan tinggi kita berada pada peringkat rendah dibandingkan dengan negara-negara tentangga, apalagi Australia, RRT, Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa, Amerika Serika dan Kanada.
Apa pun alasan dan argumentasinya, mesti para pemimpin dan penguasa negeri ini mulai sadar mengembalikan kampus sebagai par execellence, yang peran dan tugas utamanya menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara total. Hal ini harus dimulai dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan ketua-ketua lembaga tinggi negara lainnya memberikan iklim kebebasan akademi seluas-luasnya. Jika ingin manusia Indonesia menjadi manusia unggul di segala sektor di dunia ini. Dan itu semua kuncinya kebebasan akademik.
*Pernah jadi aktivis mahasiswa

 REDAKSI
REDAKSI