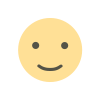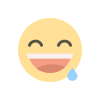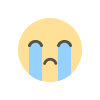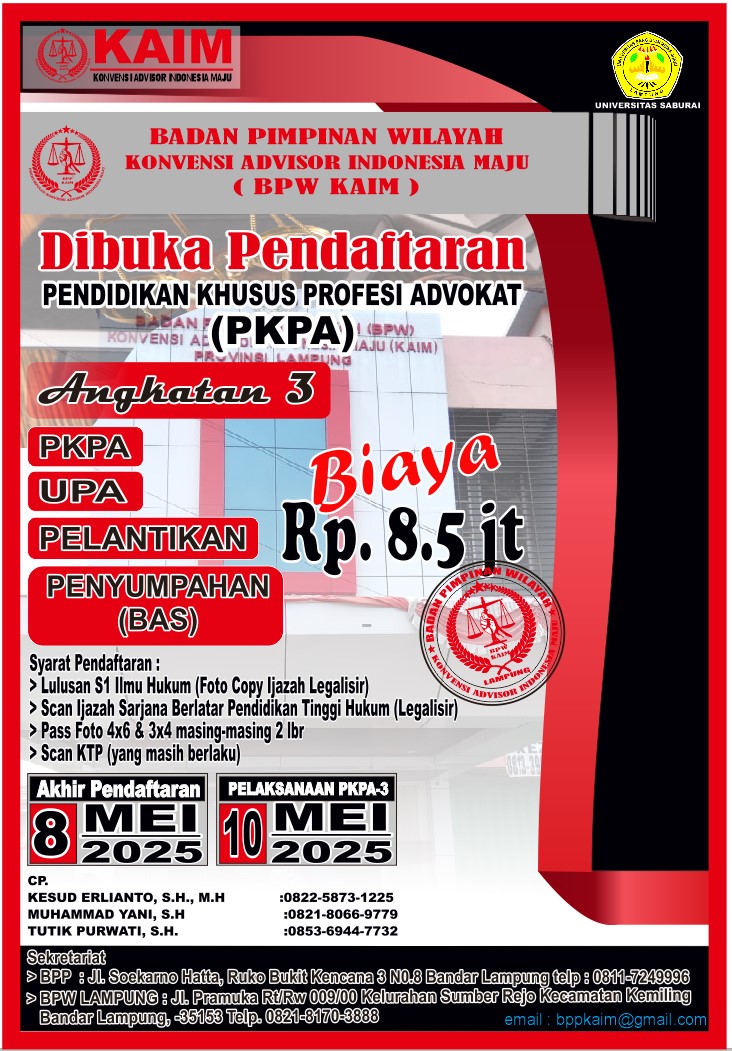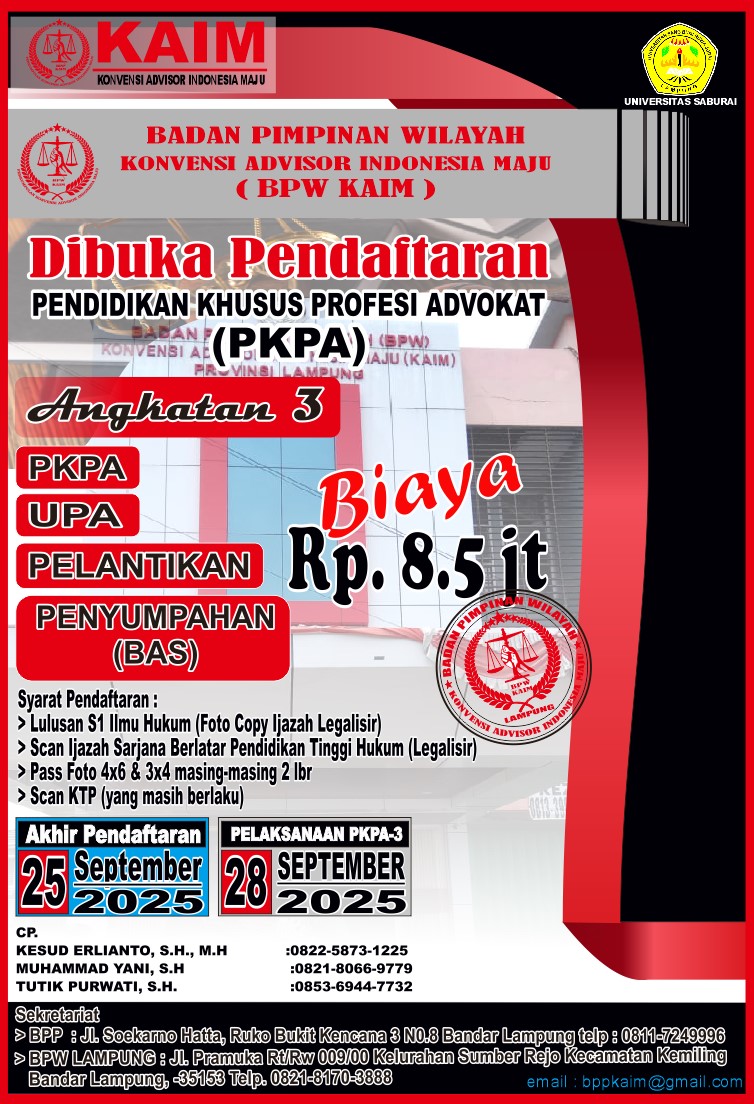Bacaan Awal 2021: Nasib Orang Kecil dan Para Pemungut Sampah Belum Membaik
Oleh: Bagong Suyoto*
PARA penjaga bumi, pelestari lingkungan nasibnya diabaikan para penguasa negeri. Penjaga bumi ini terdiri dari orang-orang kecil dan pengais sampah. Mereka tahu bagaimana menghargai dan merawat bumi, karena Sang Penguasa telah memberi amanah kepada semua manusia, terutama pada para penguasa.
Tokoh pemulung menyampaikan pesan, bahwa para pemimpin negeri sudah melupakan orang-orang kecil dan para pengais sampah. Kerusakan lingkungan semakin besar, seperti penebangan pohon semakin banyak, pembuangan limbah B3 sembarang dan lainnya telah menyebabkan bumi meranggas, bumi semakin panas dan kehilangann sirkulasi udara bersih dan oksigen. Lubang-lubang tambang dibiar merana. Lingkungan rusak dan tercemar akibat sampah, limbah berbahaya dan beracun (B3) padat dan cair dibiarkan semakin meluas terutama di perkotaan dan pinggiran pesisir dan laut. Akibatnya banjir sampah, terutama plastik, styreform hingga batang kayu menmpuk di sungai dan laut.
Para tetua adat, raja, sultan, tokoh dan pemimpin sejak zaman pra-sejarah, zaman sejarah kerajaan hingga terbentuknya republik Indonesia ini diberi amanah dari Sang Penguasa agar menjaga dan melestarikan bumi yang dipijak dan dihuni. Mereka pun dititipi orang-orang kecil dan para pengais sampah yang hidup di Indonesia. Bahkan, para pemimpin tertinggi Indonesia menggunakan simbol dan dapat hikmah dari kekuatan kegaiban bumi, berupa “Tunggul Wulung”. Suatu kekuatan gaib dari Sang Pencipta yang berada di tanah Jawa. Hal ini dapat diartikan Tunggul adalah pemimpin yang unggul, sedang Wulung berarti kecenderungan bawaan yang tersembunyi. Tunggul Wulung bisa dalam bentuk pusaka keris, bendera dari Turki atau kekuatan yang tersimpan dalam bumi. Kekuatan tersebut bisa untuk menolak balak (pagebluk).
Para pemimpin itu dititipi orang-orang kecil dan pengais sampah yang hidup serba miskin. Orang-orang kecil dan para pemungut sampah setidaknya diakui atau tidak telah memberikan suara dan meletigimasi Presiden, Wakil Presiden, para wakil rakyat di Senayan, para gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Pada saat momen Pilpres, Pileg dan Pilkada, suara orang-orang kecil dan pengais sampah sangat dibutuhkan untuk menyumbang suara kemenangan, di luar kelas menengah (middle class) dan kaum milenial. Sayangnya, setelah mereka berkuasa secara perlahan melupakan nasib orang-orang kecil dan pengais sampah ini.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan, laporan The Global Hunger Index (2019) menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Diperkirakan 8,3 persen populasi tak mendapat gizi cukup, serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting (kekurangan gizi kronis). Hal ini harusnya menjadi pengingat agar segera membenahi sector panganan. (Detinews, 29/7/2020). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 167 juta jiwa.
“Jika di masa normal saja kondisi pangan bisa sesulit itu, apalagi di kondisi pandemic COVID-19. Badan Pangan Dunia (FOA) sudah memperingatkan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya suplai karena pandemic COVID-19. Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi Indonesia untuk serius membenahi sektor pangan. Pembangunan desa harus digenjot sehingga para pemuda tak lagi melakukan urbanisasi. Pemuda harus bangga menjadi petani, terang Bamsoet.
Presiden Jokowi memperhatikan situasi tersebut dan segera membangun food estate, luasnya ratusan hingga ribuan hektar. Tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketahanan pangan. Presiden merespon peringatan FAO. Salah satu lokasinya eks proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 165 hektar, kemudian Bengkulu, Sumatera Utara, dll. Presiden mengakui, bahwa food estate mengalami kendala penyediaan lahan.
Sementara itu Biro Pusat Statistik (BPS, 2020) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,45 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang pada terhadap Maret 2019. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentasi penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.
Uwe Kracht (2002) menulis dalam “The relationship between poverty reduction and realization of the right to food”, bahwa kemiskinan itu dapat dilihat dari berbagai dimensi. Intinya dalam istilah yang lebih luas adalah deprivasi secara material: tidak cukup uang, pekerjaan, pangan, pakaian, rumah, kombinasi ketidaklayakan antara akses pelayanan kesehatan dan air bersih.
Kelompok yang rentang terhadap pangan luar biasa paling terdampak akibat masa pandemic COVID-19 dan ketika masa normal adalah orang-orang kecil dan para pemungut sampah yang mobile maupun yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Jumlah mereka jutaan orang. Orang miskin, pemulung, petani subsisten, buruh tani, korban bencana, dll termasuk food-insecurity vulnerable groups. Padahal kecukupan pangan itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Keluarga pemulung untuk mencukupi pangan, menu makan sehari-hari sangat sederhana, nasi beras pera (kualitas buruk), dengan lauk ikan asin/gesek, teri, tahu/tempe, sayur asem dan sambel. Anak-anaknya yang masih kecil diberi makan seperti yang dimakan orang tua. Hampir tiap hari mereka pun memungut sisa-sisa makanan, buah-buahan, sayuran, ikan gesek, dll dari tumpukan sampah di TPA, yang berasal dari buangan restoran, pasar, dll. Mereka beralasan yang penting bisa makan hari ini, besok cari lagi. Mereka tidak punya stok pangan, apalagi pangan yang berkualitas.
Tri Rismaharini Menteri Sosial RI yang baru belum lama ini menyambangi rumah pemulung yang ada di kolong jembatan Kali Ciliwung (Kompas, 28/12/2020). Hidup mereka sangat menyayat hati. Risma akan mengupaya rumah layak huni sekaligus memberikan pelatihan pada mereka demi perbaikan kualitas hidup.
Menteri Sosial dan Menteri lainnya harus melihat langsung kondisi orang-orang miskin dan para pengais sampah baik yang ada di perkotaan, terutama yang tinggal di bawah jembatan, kolong tol, pinggir kali maupun pinggiran pembuangan sampah. Sebetulnya para Menteri dan pejabat tinggi sudah tahu fakta dan informasi yang diberikan padanya dari belasan tahun lalu. Fakta kemiskinan dan kekumuhan itu tampak semakin permanen membesar.
Bayangkan hingga 23 Desember 2020, progress realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun, hampir Rp 700 triliun. Memang ada dua klaster dalam program PEN mencatat pencapaian 90 persen, yakni klaster perlindungan social mencapai 94,7 persen atau Rp 217,99 triliun dari alokasi anggaran Rp 230,21 triliun, dan klaster UMKM mencapai realisasi 92,8 persen atau Rp 107,93 triliun dari alokasi anggaran Rp 116,31 triliun.
Sayangnya, program PEN belum menyentuh para pengais sampah? Apa yang salah dengan para pengais sampah? Pemulung merasa diacuhkan oleh pemerintah.
Para pengais sampah sejak tahun 1960-an atau 1970-an telah bekerja nyata menerapkan 3R (reduce, reuse, recyle) sampah. Mereka ikut membersihkan kota, mengurangi sampah sampai dari TPS hingga TPA/TPST. Pekerjaan sector informal itu menciptakan lapangan kerja, selanjutnya membangkitkan pabrikan-pabrik daur ulang sampah yang menyerap ribuan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Jasa pengais sampah sangat besar bagi masyarakat dan negara tetapi tidak mendapatkan penghargaan layak dari pemerintah.
Ananda Lee Tan dalam Bagong Suyoto (Potret Kehidupan Pemulung – Dalam Bayangan Kemiskinan dan Penindasan, 2015) mengatakan, lebih kurang 15 juta penduduk di seluruh dunia tergantung pada aktivitas mengais sampah dan pengembalikan sumber daya dari sampah. Pendeknya sebagai pemulung. Recovery sumber daya melalui guna ulang, daur ulang dan composting menciptakan lapangan kerja ketimbang penanganan sampah dengan pendekatan menggunakan insinerator (mesim pembakar massal) dan pembuangan akhir sampah. Suatu contoh di Amerika Serikat, daur ulang berkelanjutan memberikan peluang kerja 10 kali lipat per ton sampah ketimbang diolah dengan mesin insinerator atau landfilling.
Dalam konteks ini sebaiknya, olah sampah menggunakan prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan composting. Apalagi Indonesia merupakan negara agraris, sampah kita adalah mayoritas organik merupakan bahan pupuk organik yang potensial. Kompos dijadikan penyubur tanah dan tanaman. Ini bagian dari upaya menjalankan sistem keberlanjutan bumi, yaitu pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Suatu paradigma dan praktek pertanian alami, dikenal di seluruh dunia.
Sedang sampah an-organik dimanfaatkan pemulung, pelapak, sektor informal, seterusnya dikirim ke pabrikan daur ulang. Dampak aktivitas bisnis daur ulang sampah bergerak dinamis, memberi ruang gerak bagi pemulung, lapangan kerja, dan income serta menyumbangan pendapatan bagi negara. Juga sebagai upaya mengembalikan sampah menjadi sumber daya. Dengan kata lain, tindakan ini adalah hemat sumberdaya. Suatu sikap yang begitu bijaksana, melebihi pandangan pemimpin dunia terkemuka. Mereka ini sebagai penjaga Bumi. Jika Anda peduli terhadap lingkungan dan kelola sampah, berarti Anda adalah orang paling bijaksana dan teladan bagi dunia! Jika tidak, Anda hanyalah aktor konyol, bombastis dengan “omong besar”.
Konsep, prinsip dan strategi 3R itu sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012, Perpres No. 97/2017. Juga berhubungan erat dengan Sejalan dengan upaya-upaya konstruktif pelestarian lingkungan hidup sesuai amanat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam thesis Bagong Suyoto (2016) disebutkan, sampah memiliki arti bukan hanya sisa atau harus disingkirkan jauh-jauh. NIMBY, Not in my backyard. Sejumlah negara NIMBY menjadi sindrom, seperti diungkapkan Al-Gore dalam Earth in the Balnace Ecology and The Human Spirit (2006). Tetapi bagi kelompok tertentu memiliki arti yang luar biasa. Didalamnya ada berkah, yang dapat menghidupi manusia dan hewan. Oleh karena itu kita harus bertindak lebih arif dan bijaksana dalam memperlakukan sampah, apalagi sampah yang berasal dari rumah sendiri. “Anda yang menghasilkan sampah, Anda yang merasa lebih jijik dan mengapa orang lain yang harus bertanggung jawab?” Suatu paradog cara pikir (mindset) yang harus ditata-ulang atau didaur-ulang!
Jutaan pemulung beraktivitas di sekitar wilayah Jabodetabek, namun belum ada otoritas yang punya data valid dan akurat. Sebanyak 6.000 pemulung di TPST Bantargebang, 400 pemulung di TPA Sumurbatu, 200 pemulung di TPA Burangkeng, dll – apa pun pandangan pemerintah – telah memberikan kontribusi cukup konkrit. Mereka mereduksi sampah an-organik lebih dari 70% dari total sampah an-organik, seperti plastik, kertas, beling/kaca, logam, karet, busa, kayu sampah tulang. Sampah an-organik menjadi urusan pemulung, tinggallah sampah organik yang belum tertangani. Pemulung bekerja dengan prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), seperti yang dikampanyekan banyak pihak. Jutaan pemulung sudah menikmati tambang emas hitam itu.
Mereka bermukin dan beranak pinak di sekitar kedua TPST/TPA tersebut. Separoh diantara mereka adalah pemulung pendatang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dll. Mayoritas pemulung berasal dari Babelan, Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Jonggol, Banten, Madura.
Sebagian besar pengais sampah di TPA tersebut adalah penduduk asli. Dulu mereka bekerja di sektor pertanian, kerajinan rakyat, sektor informal, tukang ojek, dll. Belakangan karena aset produksi lenyap berpindah ke sektor persampahan, ada yang menjadi pemulung, kuli sortir/ cuci plastik, pelapak skala kecil, dll. Mereka telah menikmati berkah dari sampah. Akibat tumbuhnya pembangunan berbagai sektor dan arus urbanisasi mengalami pergeseran pekerjaan.
Khususnya pemulung di Bantargebang dan sekitar. Pemulung pendatang pada umumnya menempati gubuk-gubuk kardos, triplek, karung/terpal, seng bekas yang tersebar di Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dan Desa Taman Rahyu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
Kondisi gubuk-gubuk komunitas pemulung itu merupakan suatu panorama sangat mengenaskan bagi sebuah kehidupan dan peradaban. Permukiman mereka berada dalam lingkungan tercemar, kumuh, jorok, sangat bau dan sanitasi sangat buruk. Kondisi demikian diperparah adanya banjir. Sejumlah pemukiman pemulung menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Pertama, karena letaknya yang rendah, dulunya bekas galian tanah atau sawah tadah hujan. Kedua, tidak ada saluran air.
Eksistensi pemulung disini sebagian besar dibawa para bos, seluruh hidup pemulung diabdikan padanya. Bos telah menyediakan tanah dan gubuk-gubuk sederhana dan sangat kumuh, beras, uang makan/dapur, uang jajan anak-anak, dll. Semuanya diperhitungkan sebagai hutang, yang harus diangsur dari hasil pungutan sampah. Bos menerapkan sistem ijon atau rente minimal 10-20%/bulan atau lebih. Sistem ijon memberatkan dan menjerat leher pemulung. Nyaris sebagian besar pemulung terlilit hutang dan terjerat rente. Jahatnya riba! Maka riba itu haram hukumnya! Buahnya kemiskinan dan penderiatan yang semakin medalam.
Orang luar komunitas ini sering salah tafsir, bahwa pemulung tak perlu dibantu karena sudah mempunyai pendapatan besar!? Hidup pemulung pas-pasan, untuk makan dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah sangat berat. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 hampir setahun lamanya kehidupan pemulung makin parah. Keuntungan dari pungutan sampah tidak seberapa, ya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan banyak pemulung tak mampu menyekolahkan anak. Ada juga pemulung dan keluarga tidak bisa Idhul Fitri atau lebaran di kampung, bahkan tak mampu beli daging atau ayam. Untung masih ada tetangga yang ingat, mengantar makanan dengan lauk daging.
Hampir semua pemulung di kawasan TPST/TPA hidup sangat sederhana dan tergantung pada bos-bos/pelapak. Mereka mendiami gubuk-gubuk dari bambu dan triplek bekas, kardos, seng, terpal bekas, karung bodol. Peralatan rumah tangga sangat sederhana, namun diantara pemulung mempunyai tv, tape recorder, cd player lengkap dengan salon stereo, dan elektronik lainnya standar murah. Peralatan elektronik seperti tv dan cd player menjadi pelengkap dan hiburan di saat para pemulung sedang penat dan lelah. Sebagai manusia pemulung pun butuh hiburan dan hidup berkecukupan.
*Founder Komite Aksi Pengolahan Sampah Indonesia (KAPSI)
*Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

 REDAKSI
REDAKSI