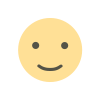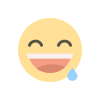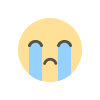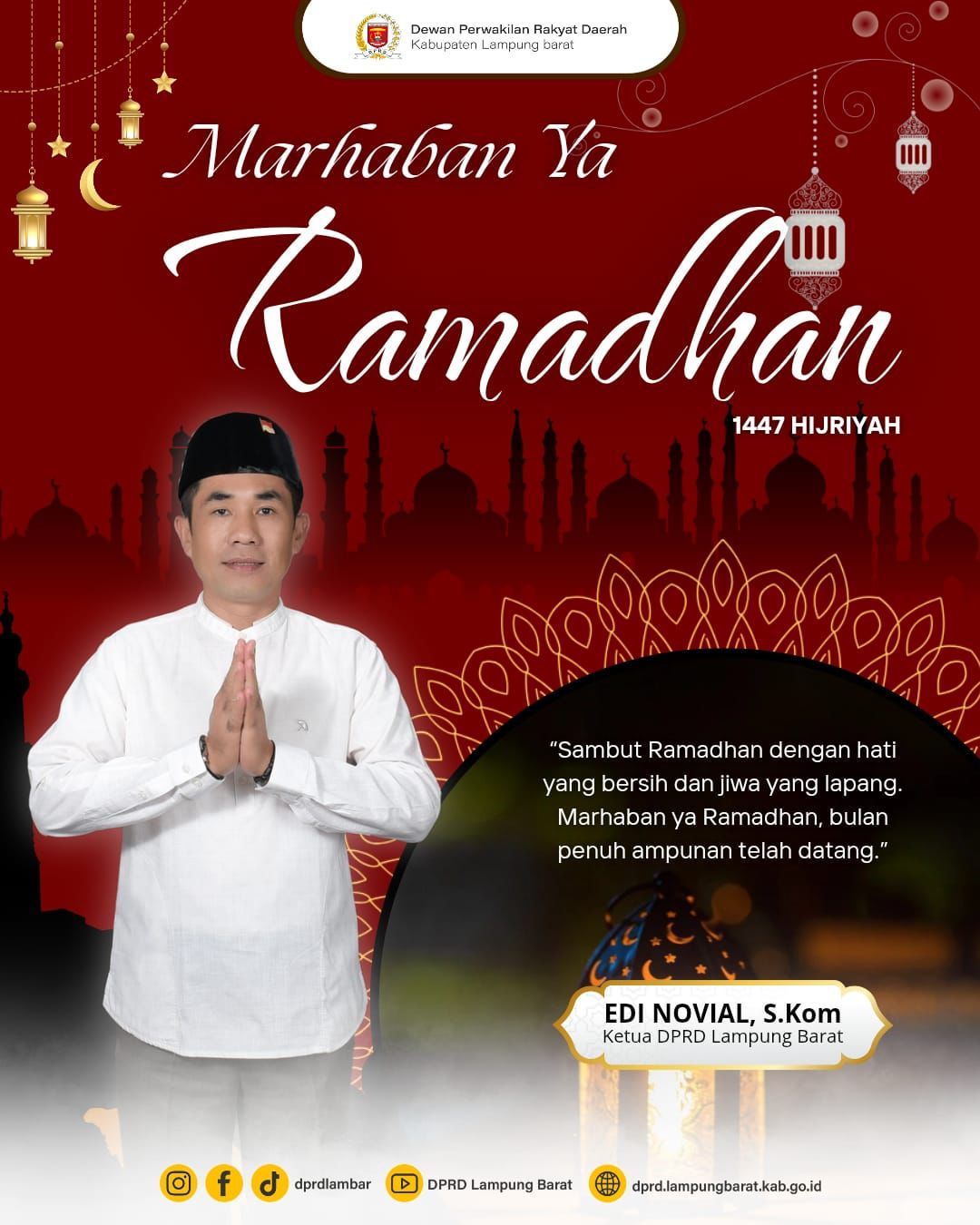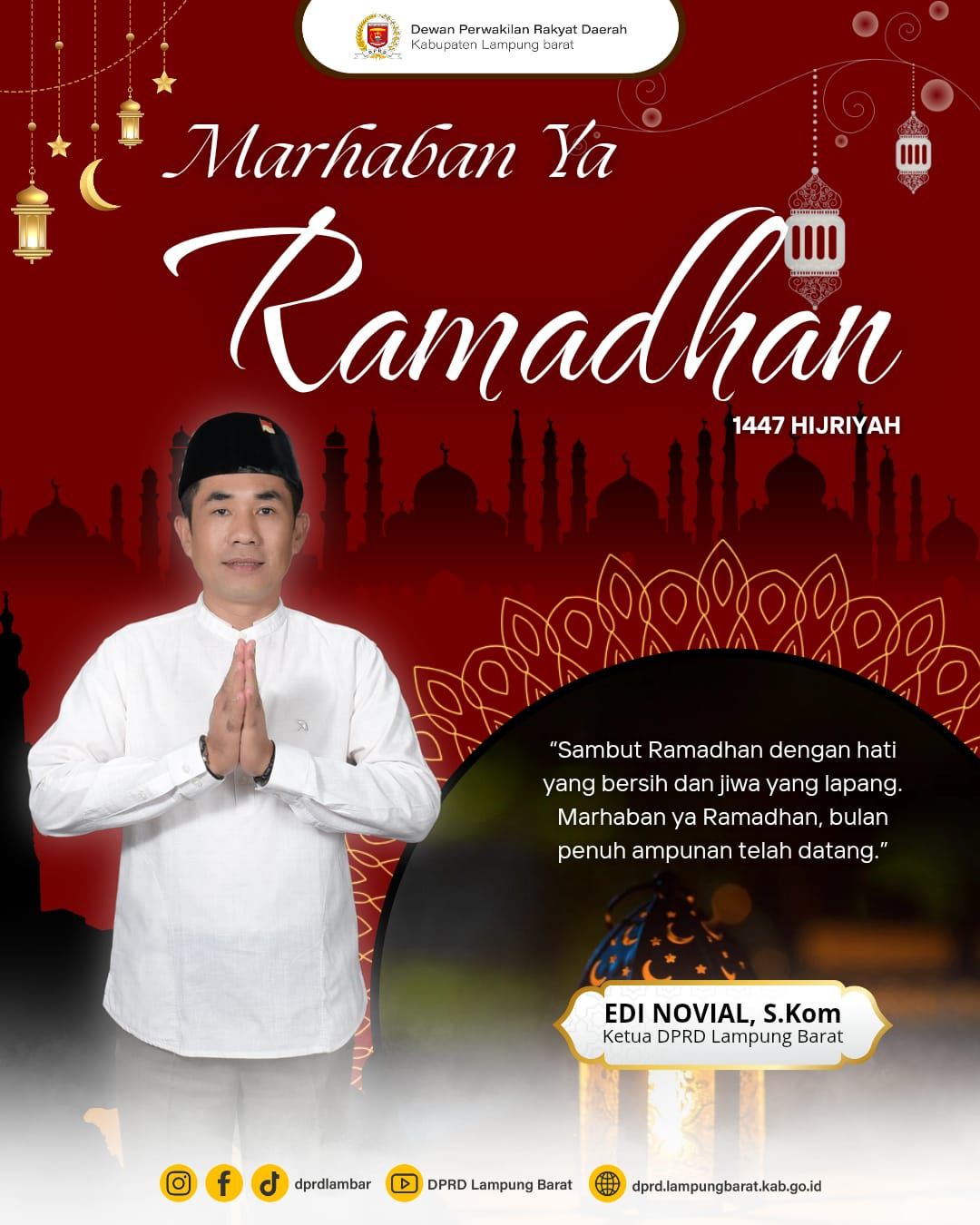Meluruskan Tuduhan, Menegakkan Fakta: Klarifikasi Zulhas tentang Banjir Sumatra dan Taman Nasional Tesso Nilo

Oleh: Prof. Gusti Hardiansyah *)
Di tengah derasnya arus informasi yang berkelindan di media sosial, satu hal yang kerap hilang adalah ketenangan dalam memeriksa fakta. Tuduhan mudah dilemparkan, kecurigaan cepat menyebar, dan reputasi publik sering menjadi korban sebelum kebenaran diberi ruang untuk bicara. Inilah konteks yang mengiringi pidato Zulkifli Hasan dalam Penutupan Silaknas dan Milad ke-35 ICMI di Bali.
Di hadapan para cendekiawan, tokoh agama, serta pemimpin nasional, Zulhas meluruskan tuduhan bahwa dirinya—ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan—menjadi penyebab banjir besar di tiga provinsi Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan nada tenang namun tegas, Zulhas membuka klarifikasinya. Ia menyadari bahwa isu yang menyangkut lingkungan dan keselamatan rakyat tidak boleh dijawab dengan emosional. Ia memilih jalur data, geografi, dan administrasi. Dan penyampaiannya menjadi penting bukan semata sebagai pembelaan diri, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijakan publik harus dibahas dengan ketelitian, bukan dengan prasangka.
Geografi yang Diabaikan: Tesso Nilo Ada di Riau, Banjir Terjadi di Aceh–Sumut–Sumbar
Salah satu inti tuduhan yang beredar adalah bahwa kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi pemicu banjir di tiga provinsi lain. Namun, dalam penjelasannya, Zulhas mengungkapkan fakta paling mendasar yang sering luput: Taman Nasional Tesso Nilo berada di Provinsi Riau, bukan di Aceh, bukan di Sumatera Utara, dan bukan di Sumatera Barat—provinsi yang mengalami banjir.
Secara geografis, kesimpulan bahwa Tesso Nilo penyebab banjir di tiga provinsi itu jelas tidak mungkin. Jika daerah yang dituduhkan berada ratusan kilometer dari lokasi banjir, maka hubungan sebab-akibatnya secara ilmiah gugur. Lebih jauh, Zulhas menegaskan bahwa Riau tidak mengalami banjir pada periode bencana yang menjadi sorotan.
Fakta ini menempatkan diskursus pada jalur yang semestinya: bahwa setiap tuduhan harus diuji pada ruang dan waktu di mana peristiwa itu terjadi.
Tidak Ada Izin Baru di Tiga Provinsi yang Mengalami Banjir
Zulhas melanjutkan klarifikasinya dengan memaparkan aspek administratif. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan, ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun izin pemanfaatan hutan, pelepasan kawasan, atau izin ruang yang ia keluarkan untuk Aceh, Sumut, maupun Sumbar.
Alasannya sederhana dan faktual:
sejak era Orde Baru, lahan di tiga provinsi tersebut telah dialokasikan seluruhnya, sehingga secara administratif tidak mungkin ada izin baru yang dikeluarkan di masa jabatannya.
Dengan demikian, tuduhan bahwa banjir dipicu oleh izin kementerian menjadi tidak berdasar secara hukum. Yang tersisa adalah persoalan lingkungan lama yang membutuhkan penataan ulang, bukan tudingan personal.
Tesso Nilo: Kerusakan Sesungguhnya adalah Perambahan, Bukan Kebijakan
Penjelasan Zulhas semakin gamblang ketika ia masuk ke isu Tesso Nilo itu sendiri. Taman nasional seluas lebih dari 83.000 hektare itu adalah kawasan konservasi yang secara aturan tidak boleh diberi izin kegiatan perkebunan. Karena itu ia menyatakan: “Tidak mungkin menteri mana pun memberikan izin di taman nasional.”
Kerusakan Tesso Nilo yang saat ini banyak diberitakan bukan akibat izin pemerintah, tetapi akibat perambahan besar-besaran yang melibatkan lebih dari 40.000–50.000 orang. Perambahan berlangsung selama bertahun-tahun, terutama pada masa awal reformasi, ketika penegakan hukum melemah dan pemerintah daerah mengalami tekanan politik lokal yang sangat kuat.
Zulhas menyebut fenomena itu sebagai “surplus demokrasi”—ketika kebebasan tumbuh lebih cepat daripada kapasitas sistem untuk menegakkannya. Aparat daerah tidak berani bertindak, sementara perambahan makin masif. Hasilnya adalah fragmentasi habitat, konflik satwa, dan kerusakan ekosistem yang tidak sempat dikendalikan.
Tesso Nilo, dalam hal ini, menjadi simbol kegagalan penegakan hukum masa lalu, bukan kegagalan kebijakan menteri yang sedang disalahkan.
4 Juta Hektare Perambahan Ilegal Berhasil Diambil Alih Negara
Bagian paling menarik dari klarifikasi Zulhas adalah perbandingan antara masa lalu dan masa kini dalam penertiban kawasan perambahan. Ia mengaku pernah mengalami sendiri betapa sulitnya menindak perambahan hutan: operasi terhenti, pesawat tidak bisa mendarat, aparat mendapat perlawanan, bahkan bertahan selama tujuh hari tanpa hasil.
Namun ia menggarisbawahi bahwa di era pemerintahan sekarang, operasi terpadu — melibatkan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta KLHK — berhasil menertibkan 4 juta hektare kebun ilegal dalam waktu yang relatif singkat. Termasuk kawasan-kawasan yang sebelumnya tidak tersentuh seperti bagian dari Tesso Nilo, Sumatera Utara, dan wilayah-wilayah lain.
Ini menunjukkan bahwa masalah bukan terletak pada izin, tetapi pada skala perambahan dan ketidakmampuan penegakan hukum masa lalu. Ketika negara kembali hadir dengan perangkat yang solid, penataan ruang dapat dilakukan secara tegas.
1,6 Juta Hektare: Penataan Ruang, Bukan Izin Baru
Isu lain yang juga dikaitkan secara keliru adalah penetapan 1,6 juta hektare lahan. Banyak pihak menuduhnya sebagai pemberian izin baru, padahal esensinya berbeda. Zulhas menjelaskan bahwa angka tersebut adalah penataan ruang terhadap:
kampung tua,
wilayah adat,
jalan dan fasilitas umum,
pemekaran daerah,
kota dan pasar yang berkembang secara organik.
Penataan ruang dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi permukiman dan fasilitas publik yang sudah ada jauh sebelum negara memetakan ulang ruangnya. Tidak ada penambahan perkebunan, tidak ada ekspansi baru, tidak ada izin yang dilepaskan untuk kepentingan korporasi.
Di sini, klarifikasi Zulhas memulihkan posisi pemerintah sebagai penyedia kepastian ruang, bukan sebagai pemicu bencana seperti yang dituduhkan.
Penutup: Ketelitian Fakta sebagai Dasar Moral Publik
Klarifikasi Zulhas bukan hanya membela diri. Ia menawarkan pelajaran penting bagi publik: bahwa dalam ekosistem informasi yang gaduh, kebenaran memerlukan ketekunan, bukan asumsi. Banjir Sumatra adalah masalah kompleks yang terkait hidrologi, kerusakan DAS, dan perubahan tata guna lahan jangka panjang.
Menyederhanakannya pada satu nama bukan saja tidak adil, tetapi juga mengaburkan akar masalah yang harus diselesaikan bersama.
ICMI, sebagai rumah besar cendekiawan Muslim, memiliki peran strategis dalam merawat ketelitian, rasionalitas, dan keadilan dalam membaca kebijakan publik. Klarifikasi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia—dalam kerangka Pancasila—membutuhkan nalar yang jernih, hati yang adil, dan kesediaan untuk melihat fakta apa adanya.
*)
Guru Besar Universitas Tanjungpura — Ketua ICMI Kalimantan Barat

 REDAKSI
REDAKSI