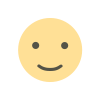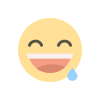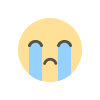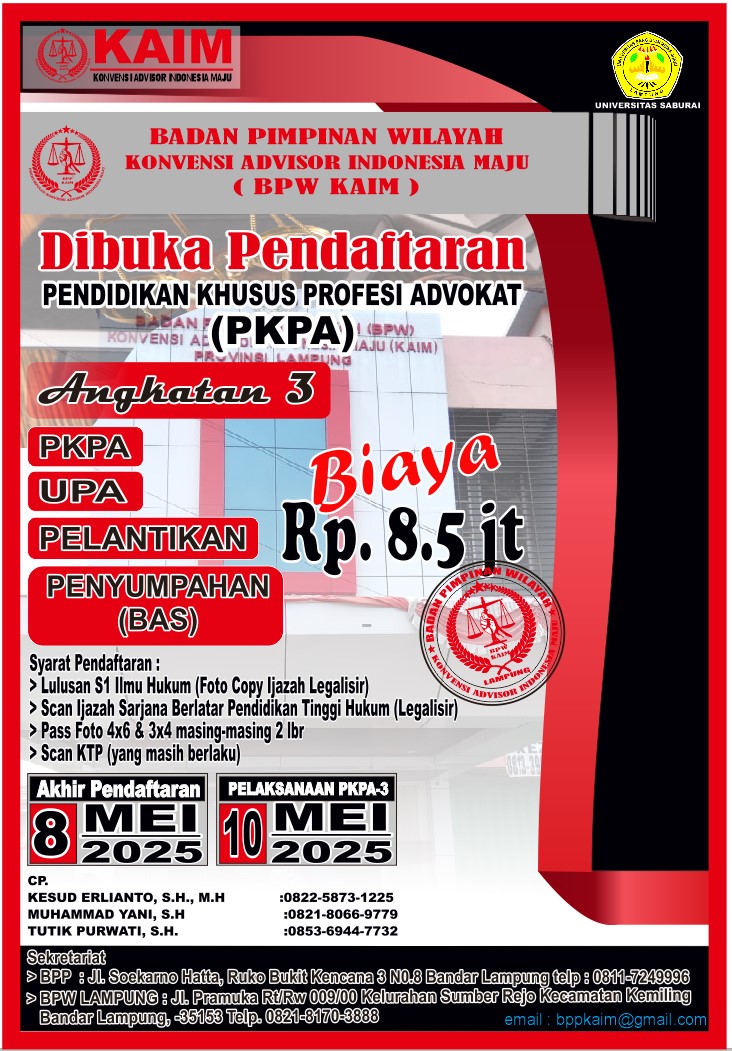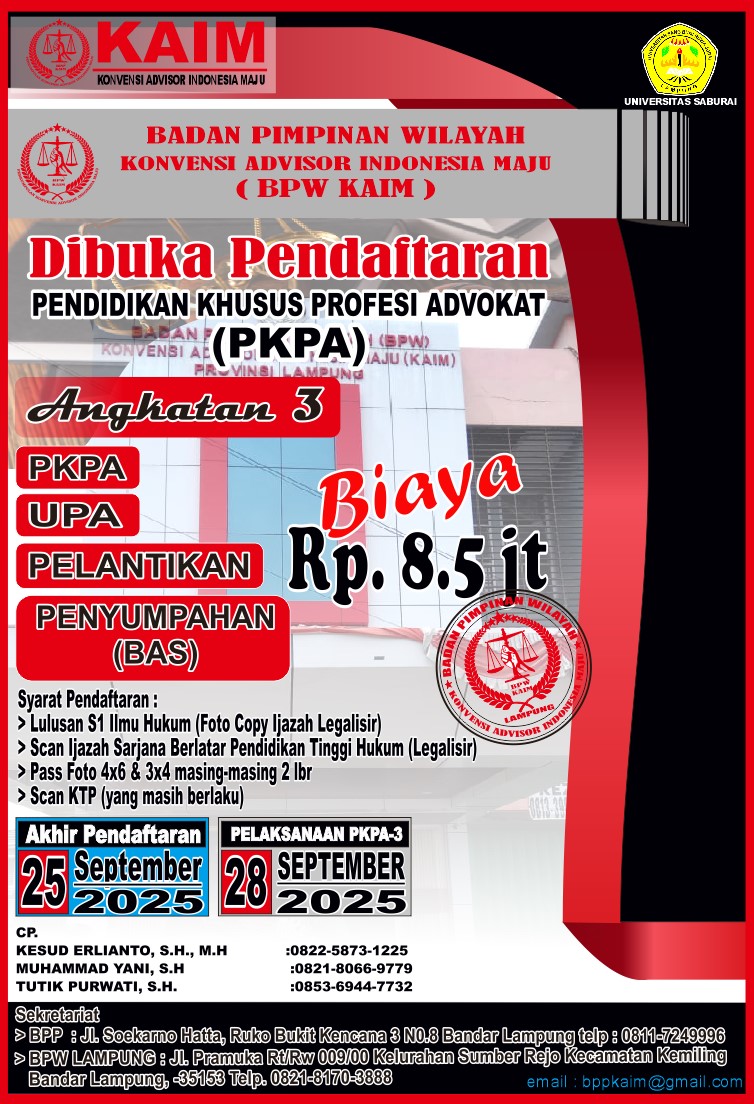Disaster Management ditengah Pandemi
Oleh: Muhammad Sutisna*
PADA setiap tahunnya, hari demi hari Indonesia tidak pernah lepas dari fenomena bencana alam mulai dari banjir, tsunami, gempa, longsor, kecelakaan transportasi hingga gunung meletus. Dimana kondisi tersebut sangatlah wajar bila melihat letak geografis Indonesia yang berada dalam patahan tektonik dan lain sebagainya.
Ketika melihat kondisi hari ini, Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang terus menghantui. Sehingga ketahanan nasional suatu bangsa saat ini sedang betul betul diuji. Karena fokus terhadap penanganan pandemi, disisi lain harus sigap dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi.
Seperti peristiwa bencana yang berlangsung berturut-turut saat ini, mulai dari jatuhnya pesawat sriwijaya air, longsor di sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, hingga gempa yang terjadi di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Belum lagi dengan status Gunung Merapi yang kini udah mulai batuk-batuk.
Nampaknya dalam menghadapi setiap bencana kita selalu terlihat gugup akibat dari kurang maksimalnya disaster management tersebut. Padahal sangat penting untuk meminimalisirnya terjadinya dampak akibat dari sebuah bencana. Karena dalam hal manajement kebencanaan, yang dikaji itu bukan hanya setelah bencana terjadi. Tapi bagaimana memprediksi sebuah bencana yang terjadi untuk selalu sigap. Masih kurangnya early warning dan early detection dalam menghadapi before maupun afternya dari sebuah bencana.
Belajar dari pengalaman beberapa negara maju yang rawan bencana seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa, bahwa secara umum, kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan telah tumbuh serta berkembang melalui pelatihan secara teratur. Karena pemerintahnya sudah memiliki kemampuan manajemen bencana yang baik dan disisi lain didukung penuh oleh kesadaran masyarakatnya.
Bahkan bila merujuk hasil survei di Jepang, pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995, menunjukkan bahwa presentase korban selamat disebabkan oleh Diri Sendiri sebesar 35%, Anggota Keluarga 31,9 %, Teman/Tetangga 28,1%, Orang Lewat 2,60%, Tim SAR 1,70 %, dan lain-Lain 0,90%.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, sangat jelas bahwa faktor yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh “diri sendiri” untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman risiko bencana. Kemudian, diikuti oleh faktor bantuan anggota keluarga, teman, bantuan Tim SAR, dan di sekelilingnya.
Perlu adanya proses penyadaran agar setiap orang dapat memahami risiko, mampu mengelola ancaman dan pada gilirannya dapat berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana.
Di samping itu, kohesi sosial, gotong royong, dan saling percaya merupakan nilai perekat modal sosial yang telah teruji dan terus dipupuk, baik kemampuan perorangan dan masyarakat secara kolektif, untuk mempersiapkan, merespon, dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.
Selain itu Bene (2012) menyatakan bahwa sebagai suatu proses ketahanan sosial dan budaya sadar bencana dalam jangka panjang, perlu adanya ketangguhan masyarakat yang terdiri dari tiga elemen yaitu: kapasitas meredam ancaman (absorptive) yang menghasilkan persistensi, kemampuan beradaptasi (adoptive) yang menghasilkan penyesuaian perlahan dan berjangka panjang, dan kapasitas bertransformasi (transformative) yang menghasilkan respon- respon transformasional.
Memang kita tidak bisa mendahului sebuah takdir. Namun dengan hadirnya disaster management ini adalah bentuk kehadiran negara dalam meminimalisir dampak yang terjadi. Selain itu dengan kekuatan civil society yang ada di Indonesia, setidaknya menjadi harapan untuk bisa saling merekat solidaritas antar elemen bangsa dalam menghadapi setiap bencana. Karena duka mereka adalah duka kita semua. #PrayForIndonesia.
*Mahasiswa S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia

 REDAKSI
REDAKSI